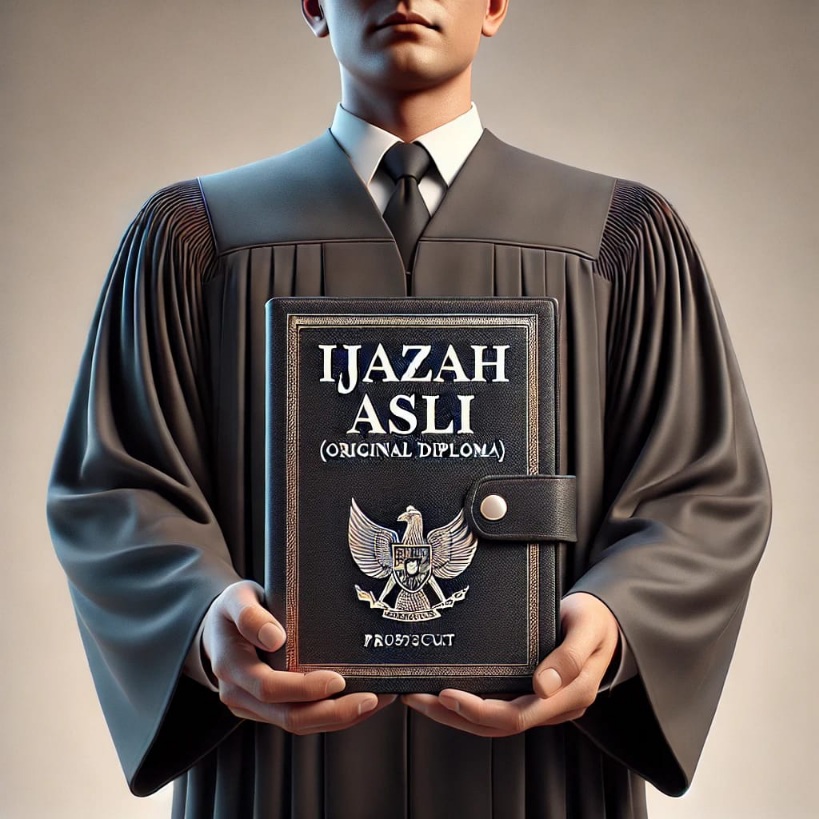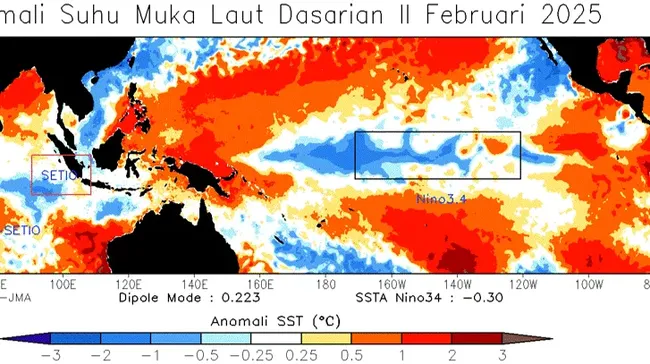FOTO : ilustrasi orang halal bihalal [ ist ]
SUDAH empat tahun saya dan istri menetap di rumah mungil kami di Pontianak Kota. Bagaimana saya tahu? Bukan karena cat tembok yang mulai luntur atau AC yang makin lemah tiupan anginnya, tapi karena saya menghitungnya berdasarkan jumlah open house yang kami gelar.
Empat open house, berarti empat tahun usia rumah. Matematika spiritual semacam ini belum masuk kurikulum, tapi sangat ampuh untuk mengukur waktu dalam satuan rendang dan salam tempel.
Open house tahun ini terasa istimewa. Bukan karena rumah kami tiba-tiba viral di TikTok atau ditandai Google Maps sebagai “lokasi wajib dikunjungi”, tapi karena acara ini bertepatan dengan hari ulang tahun pernikahan kami.
Tanggal yang sakral, yang dirayakan bukan dengan lilin romantis atau makan malam di restoran bintang lima, melainkan dengan deretan kursi plastik, gelas-gelas bening isi sirup, dan suara anak-anak tetangga yang berlari sambil berteriak “Bu, nambah sup kikil ya!”
Tamu yang datang luar biasa. Dari tetangga yang biasanya hanya lewat depan rumah, kini hadir duduk di sofa rumah. Teman-teman dosen datang dengan pakaian terbaik mereka, yang biasanya cuma dipakai saat jadi pembicara seminar nasional.
Guru-guru, alumni S1 yang dulu suka lupa tugas, sekarang ingat alamat rumah saya. Bahkan pejabat datang! Ya, pejabat. Walaupun saya cuma tukang ngopi, ada pejabat yang rela menanggalkan jas dan protokol hanya demi sepiring nasi kebuli dan obrolan ringan di teras. Sebuah anomali sosial yang perlu diteliti.
Karena tamu membludak, sistem parkir kami harus di-upgrade. Saya segera rekrut mahasiswa-mahasiswa saya menjadi petugas parkir temporer. Mereka, yang biasanya sibuk menunda skripsi, kini sigap mengatur mobil, memberi kode tangan, bahkan berakting seperti tukang parkir profesional. Honor mereka tidak besar, hanya cukup untuk membeli mie instan rasa soto selama sepekan. Tapi bagi mereka, itu sudah seperti THR dalam bentuk karbohidrat.
Untuk urusan makanan, saya dan istri memutuskan menyerah pada kenyataan. Kami tidak akan sanggup masak sendiri. Maka kami pesan dari katering langganan yang sudah kami percaya sejak zaman sebelum pandemi. Menu utama, nasi kebuli dengan taburan kismis yang seolah berkata, “Saya manis, tapi penuh misteri.” Sup kikil hadir sebagai jawaban atas pertanyaan hidup yang tak terjawab.
Ada patcri nanas ciri khas Melayu Pontianak. Ada es kelapa kopior pas di tengah cuaca panas. Selebihnya, kue lebaran dengan aneka rasa.
Namun di balik semua itu, saya teringat sabda Rasulullah, bahwa Islam yang baik itu memberi makan dan menyapa, bahkan pada yang tidak kita kenal. Bahwa sebaik-baik manusia adalah yang memberi makan.
Di sinilah saya merasa, open house ini bukan cuma soal nasi dan kerupuk, tapi bagian dari jihad sosial. Saya mungkin belum bisa mendirikan sekolah, tapi saya bisa mendirikan stan prasmanan.
Indonesia, negeri penuh makanan dan pertemuan. Dari lahir sampai wafat, semuanya ada upacara makan. Dilamar, makan. Nikahan, makan. Hamil, makan. Lahiran, makan. Anak khatam Quran, makan. Sampai meninggal pun, tetap makan.
Mungkin inilah sebab Indonesia relatif damai. Rakyatnya sibuk kunyah, bukan sibuk marah. Kalau setiap minggu ada hajatan, maka peluang untuk ribut bisa ditekan oleh semur daging dan lontong sayur.
Open house ini bukan sekadar ajang temu kangen. Ia adalah sistem pertahanan sosial. Ia adalah diplomasi rumahan. Ia adalah cara kami mengalahkan kesepian dengan sambal dan mengusir prasangka lewat sup hangat. Jika dunia ingin damai, mungkin mereka tinggal meniru model ini. Gelar open house. Buka pintu. Sajikan makanan. Pastikan ada nasi kebuli, atau rendah selalu cukup untuk tamu.
#camanewak
Oleh : Rosadi Jamani
[ Ketua Satupena Kalbar ]

 3 days ago
8
3 days ago
8