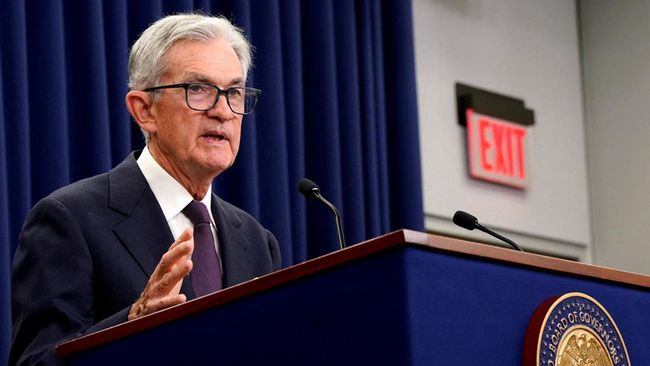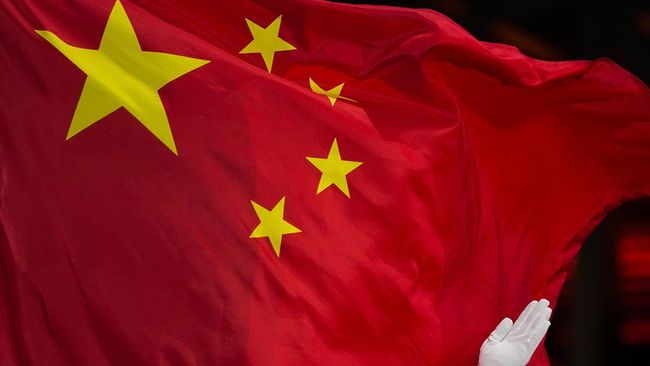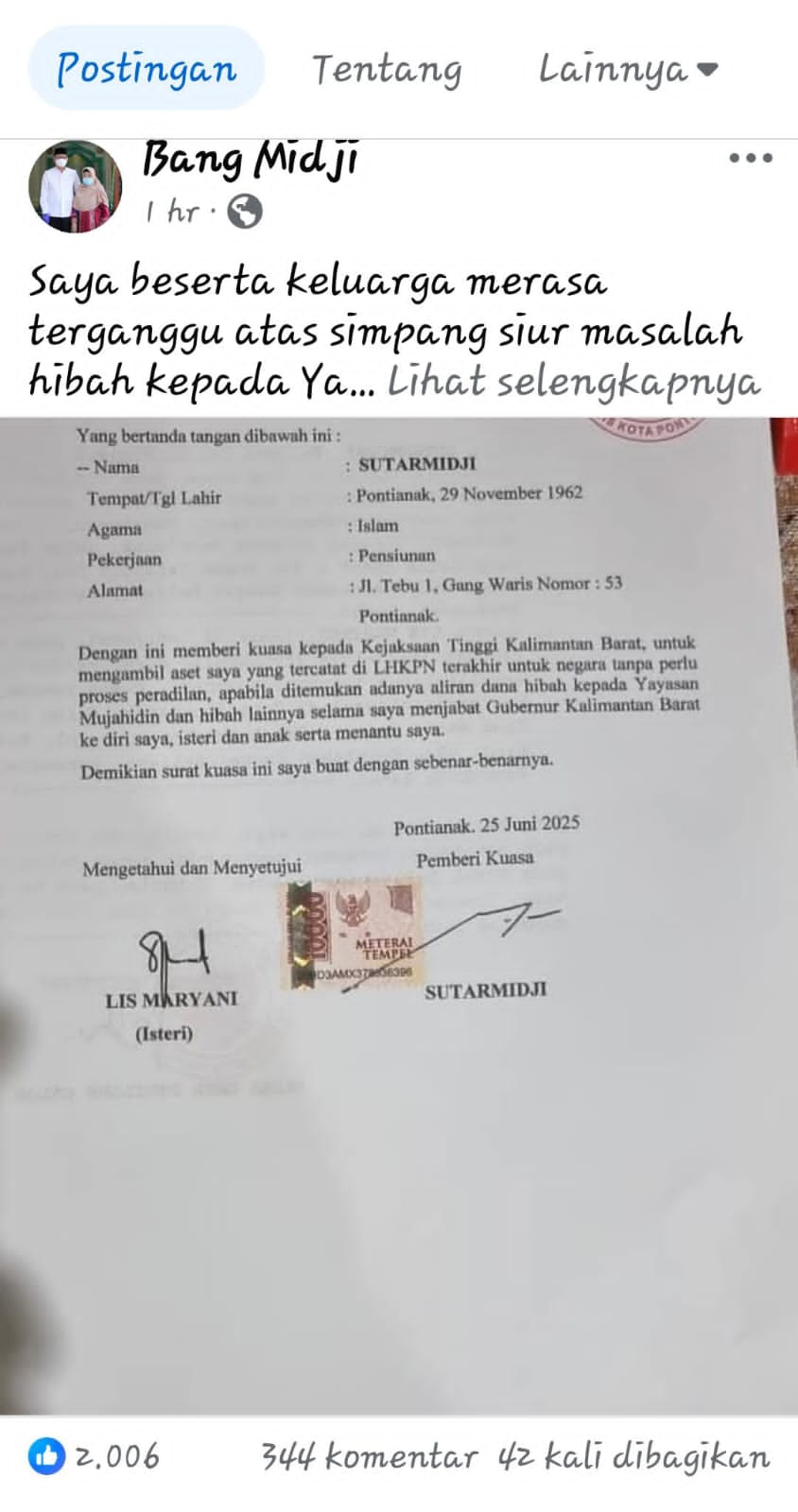Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Kebijakan dan instrumen fiskal, moneter, dan sistem keuangan (khususnya perbankan) memang memiliki ruang peran masing-masing. Regulasi juga memberikan batasan kewenangan kepada setiap institusi.
Otoritas fiskal, misalnya, kewenangannya dalam mengarahkan ekonomi terbatas dengan memainkan instrumen APBN. Yaitu, memaksimalkan instrumen pendapatan, belanja dan pembiayaan pada APBN untuk mempengaruhi perekonomian.
Otoritas moneter, sesuai kewenangannya, juga terbatas pada penggunaan instrumen moneter melalui suku bunga, uang beredar dan makroprudensial. Sementara itu, otoritas industri keuangan dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai kapasitasnya adalah mengarahkan industri keuangan agar bekerja secara sehat agar dapat mendukung arah perekonomian yang dikehendaki oleh otoritas fiskal dan moneter.
Meskipun memiliki kewenangannya sendiri, yang perlu dipahami dampak dari kebijakan yang diambil oleh setiap otoritas adalah bersifat tidak terbatas. Kebijakan fiskal, misalnya, dapat mempengaruhi pergerakan lalu lintas moneter. Begitupun sebaliknya, kebijakan moneter juga dapat mempengaruhi ruang fiskal pemerintah.
Itulah kenapa dalam setiap Nota Keuangan APBN, selalu muncul analisis sensitivitas makro ekonomi, di mana di dalamnya terdapat indikator moneter, sebagai tools untuk menghitung dampak dari setiap perubahan indikator makro ekonomi terhadap postur APBN.
Belakangan ini, dinamika perekonomian kita diramaikan oleh kebijakan penempatan dana pemerintah dari rekening di Bank Indonesia (BI) ke bank-bank BUMN. Tujuannya, meningkatkan likuiditas perekonomian dan mendorong pertumbuhan kredit.
Beberapa kalangan, menilai langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tersebut keliru. Pandangan ini didasari bahwa permintaan kredit sedang lemah, sehingga penempatan dana pemerintah tersebut dapat memicu praktek penyaluran kredit yang agresif tanpa memperhatikan risiko kredit bermasalah (non-performing loan).
Bahkan, terdapat pula yang menilai bahwa kebijakan Menkeu telah masuk ke ranah moneter, khususnya terkait peredaran uang dan likuiditas perekonomian. Sehingga tidak mengherankan bila ada yang menyebut kebijakan Menkeu tersebut sebagai "kebijakan fiskal rasa moneter".
Dalam perspektif yang lebih holistik, pandangan di atas sebenarnya cenderung mengabaikan fakta-fakta yang mendasar. Betul bahwa saat ini permintaan kredit masih rendah. Hal itu terlihat dari pertumbuhan kreditnya. Berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI), per Agustus 2025, kredit bank umum hanya tumbuh 7,09% (yoy), di mana kredit UMKM bahkan hanya tumbuh 1,29% (yoy).
Penulis berpendapat justru pada situasi ini kita perlu menggali: mengapa pertumbuhan kredit rendah? Dan mengapa pula di tengah rendahnya pertumbuhan kredit, nilai kredit yang belum disalurkan (undisbursed loan) justru tinggi?
Relasi Antara Ketatnya Likuiditas dan Tingginya Biaya Dana
Rendahnya pertumbuhan kredit setidaknya dapat dipengaruhi oleh tiga hal. Pertama, kondisi perekonomian sedang tidak baik, sehingga menurunkan minat investasi dan permintaan kredit. Kedua, meningkatnya risiko kredit, terlihat dari perkembangan angka NPL, sehingga mendorong perbankan lebih berhati-hati dalam penyaluran kredit.
Ketiga, yang tak kalah penting adalah pricing, dalam hal ini suku bunga kredit. Suku bunga kredit yang tinggi akan membatasi minat pelaku usaha meminjam kredit ke bank. Dan faktanya bahwa hasil survei BI juga mengungkap adanya kendala pembiayaan oleh dunia usaha terkait kesulitan mengakses kredit ke bank yang dikaitkan dengan tingginya suku bunga kredit.
Penulis melihat ketiga faktor di atas memiliki keterkaitan dan saling memengaruhi. Ini mengingat, tinggi rendahnya pertumbuhan kredit dan relasinya dengan pertumbuhan ekonomi sebenarnya bisa menghadirkan hubungan kausalitas.
Rendahnya pertumbuhan kredit memang bisa dipengaruhi oleh kinerja perekonomian yang lemah. Namun, dalam relasi yang lain, rendahnya pertumbuhan kredit juga dapat menjadi penyebab rendahnya kinerja perekonomian.
Sehingga, pada posisi ini, faktor suku bunga kredit dapat menjadi instrumen vital untuk mendorong kinerja keduanya, yaitu mendorong pertumbuhan kredit dan selanjutnya pertumbuhan ekonomi. Suku bunga kredit yang rendah akan meningkatkan minat atau demand kredit dan menurunkan undisbursed loan. Melalui kenaikan pertumbuhan kredit, dampak selanjutnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi.
Langkah yang diambil Menkeu dengan menempatkan dana pemerintah ke bank-bank BUMN adalah bentuk intervensi untuk mempengaruhi ketiga faktor di atas, yaitu menurunkan suku bunga kredit, meningkatkan demand dan pertumbuhan kredit dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana relasi antara penempatan dana pemerintah dengan penurunan suku bunga kredit?
Suku bunga kredit (cost of financing) memiliki relasi kuat dengan biaya dana (cost of fund). Sedangkan biaya dana biasanya dipengaruhi oleh dua hal, pertama, tingkat suku bunga kebijakan (BI Rate). Kedua, kondisi likuiditas perbankan.
Faktanya bahwa memasuki tahun 2023 hingga Mei 2025, posisi likuiditas perbankan memang turun. Likuiditas perbankan di sini adalah merujuk pada kelebihan likuiditas (excess liquidity) yang merupakan selisih antara dana pihak ketiga (DPK) perbankan dengan kredit.
Tentu ini sebuah ironi. Di tengah isu pertumbuhan dan demand kredit yang konon disebut melemah, ternyata ekses likuiditas juga menurun. Logikanya, ketika demand kredit turun, ekses likuiditas meningkat (cateris paribus). Fakta yang terjadi tidak demikian. Pertumbuhan kredit turun, likuiditas juga turun. Ibaratnya, sudah jatuh tertimpa tangga pula.
Selama periode 2023 hingga Mei 2025, bukan hanya kredit yang "kehilangan tenaga" tetapi perbankan juga menghadapi likuiditas yang ketat. Penurunan likuiditas perbankan ini terutama berasal dari kelompok deposan perseorangan, di mana per Agustus 2025, pertumbuhan DPK-nya tidak sampai 1% (yoy).
Kondisi ini memaksa perbankan membayar mahal kepada deposan untuk mencukupi kebutuhan likuiditasnya. Cost of fund naik. Siapa yang "menikmati" cost of fund yang mahal itu? Data BI memperlihatkan bahwa pertumbuhan DPK saat ini terutama ditopang oleh simpanan yang berasal dari kelompok pemilik dana institusi. Deposan institusi ini antara lain terdiri dari korporasi lembaga keuangan bukan bank, korporasi non-keuangan dan pemerintah (pusat dan daerah).
Dengan kata lain, intervensi Menkeu melalui kebijakan penempatan dana di bank umum memiliki landasan argumentasi yang kuat. Kekosongan likuiditas perbankan yang berasal dari deposan perseorangan, yang biasanya menjadi sumber dana murah bagi perbankan, perlu diisi untuk menjaga cost of fund tetap rendah. Dan disinilah peran penempatan dana pemerintah di bank-bank umum tersebut.
Relasi antara Realisasi Anggaran Dengan Biaya Dana
Tidak hanya itu, Menkeu melalui kewenangan fiskalnya juga menggunakan instrumen anggaran negara untuk menjaga cost of fund perbankan agar dapat diturunkan. Strateginya adalah monitoring realisasi penggunaan anggaran di Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah. Setidaknya, terdapat dua dimensi dari upaya monitoring yang dilakukan Kemenkeu terhadap realisasi penggunaan anggaran terhadap likuiditas dan cost of fund.
Pertama, disiplin dalam realisasi anggaran pemerintah (pusat dan daerah) akan mendorong perputaran uang lebih cepat. Kondisi ini selain akan mendorong aktivitas perekonomian (konsumsi dan investasi) juga akan mendorong kenaikan pertumbuhan likuiditas perbankan.
Kedua, bila realisasi penggunaan anggaran berjalan normal, situasi ini akan mempersempit ruang pemerintah (pusat dan daerah) untuk menempatkan dananya pada instrumen simpanan yang berdurasi lama dan berbiaya mahal (seperti deposito).
Dengan kata lain, melalui mekanisme monitoring realisasi penggunaan anggaran, Menkeu secara tidak langsung ingin mencegah praktek penempatan dana pemerintah ke perbankan pada instrumen simpanan yang justru dapat mendorong kenaikan cost of fund dan selanjutnya dapat menyebabkan kenaikan bunga kredit.
Fakta selanjutnya adalah sejak kuartal III-2022 hingga akhir tahun 2024, BI Rate cenderung meningkat. Kenaikan BI-rate tersebut dilakukan adalah dalam rangka "mengimbangi" kebijakan bank sentral Amerika Serikat yang menaikkan suku bunga acuannya the Fed Fund Rate (FFR) dalam rangka menjaga agar tidak terjadi capital outflow dan memperlemah nilai tukar Rupiah.
Memasuki tahun 2025, BI mulai melakukan pelonggaran moneter melalui penurunan BI Rate. Selama 2025, BI Rate telah diturunkan sebanyak lima kali yaitu dari 6% pada akhir 2024 menjadi 4,75% pada Oktober 2025. Sayangnya, transmisi penurunan BI Rate ke suku bunga perbankan masih berjalan lambat, setidaknya hingga Semester I-2025. Biaya dana dan suku bunga kredit perbankan masih relatif tinggi. Kembali lagi, situasi ini bermula dari ketatnya likuiditas.
Menkeu, sebelumnya adalah Kepala Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan suku bunga penjaminan (LPS Rate). LPS Rate adalah suku bunga acuan atau dapat disebut sebagai tingkat suku bunga maksimal yang dapat diberikan oleh bank kepada deposan bila ingin simpanannya di bank dijamin LPS.
Menkeu tentunya sangat memahami bagaimana relasi antara suku bunga acuan (policy rate) atau BI Rate dan LPS Rate dengan suku bunga perbankan (baik suku bunga simpanan maupun suku bunga kredit). Bila dalam faktanya, transmisi penurunan BI Rate dan LPS Rate ke suku bunga kredit perbankan tidak berjalan baik, tentu patut dicermati adanya "faktor lain yang menjadi pengganggu".
Patut diduga bahwa cost of fund masih cenderung tinggi tersebut tidak disebabkan oleh tingkat suku bunga counter rate. Dan penulis memiliki keyakinan Menkeu PYS telah memiliki data, informasi dan analisa tentang "faktor-faktor pengganggu" tersebut.
Penulis juga memiliki keyakinan bahwa penempatan dana pemerintah ke bank-bank umum serta penguatan monitoring realisasi anggaran pemerintah (pusat dan daerah) adalah dalam rangka menutup celah agar "faktor-faktor pengganggu" tersebut tidak lagi mengganggu bekerjanya transmisi kebijakan moneter ke sektor perbankan.
Inilah yang penulis sebut sebagai ketika logika fiskal, moneter dan perbankan menyatu. Dan tentunya muara dari menyatunya logika-logika ini adalah terwujudnya sasaran bersama yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.
Belanja Masalah Bersama, Bersama Selesaikan Masalah
Dalam pengamatan penulis, seluruh otoritas yang mengatur dan mengendalikan sektor keuangan, yaitu Kemenkeu, BI, OJK dan LPS, telah berada dalam satu kerangka (framework) yang sama, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. BI, misalnya, kini menjadi semakin longgar dalam kebijakan moneternya. Tidaknya hanya melalui pelonggaran instrumen suku bunga acuan, bahkan jauh sebelumnya BI telah agresif dengan kebijakan insentif pada sisi makroprudensialnya.
Hal yang sama juga dilakukan OJK. OJK kini semakin aktif menyelesaikan bottlenecking pada sisi industri keuangan terkait dengan masih lambatnya pertumbuhan aktivitas pendanaan dan pembiayaan, baik melalui perbankan, industri keuangan non-bank maupun pasar modal.
Sementara itu, LPS ibaratnya sebagai "the last commander" dalam mengawal pasar dan industri keuangan diperkirakan akan tetap konsisten menjaga ceiling rate yang mendukung bagi terwujudnya cost of fund yang semakin rendah.
Berbagai langkah para pemegang otoritas di sektor keuangan tersebut tentu belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih cepat. Percepatan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi melalui likuiditas ke perekonomian memang diperlukan.
Namun demikian, langkah tersebut perlu diikuti dengan penyelesaian hambatan teknis (debottlenecking) di sektor riilnya untuk mempercepat efektivitas kebijakan pelonggaran likuiditas. Dalam konteks ini, seyogyanya instrumen fiskal, moneter, dan sektor keuangan (khususnya perbankan) dapat menjadi trigger bagi percepatan debottlenecking di sektor riil.
Beberapa waktu yang lalu, Menkeu PYS turun menemui pelaku usaha industri rokok dalam rangka "belanja masalah" sekaligus menunjukkan bukti dukungannya kepada industri tersebut. Seyogyanya, langkah tersebut direplikasi secara meluas serta dengan skala yang lebih strategis ke sektor-sektor lainnya.
"Belanja masalah" dan sinyal dukungan terhadap industri perlu lebih banyak ditunjukkan oleh para pemegang otoritas di sektor keuangan, sesuai dengan kewenangannya. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara para pemegang otoritas di sektor keuangan dengan para pemangku kepentingan di sektoral seperti para menteri teknis serta pelaku usaha akan turut menentukan efektivitas transmisi kebijakan di sektor keuangan ke pertumbuhan sektor riil.
Mari "belanja masalah" bersama-sama, selanjutnya bersama-sama selesaikan masalah. Tujuannya, agar kebijakan di sektor keuangan semakin membumi (down to earth) sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan industri. Penulis berpendapat, hanya dengan cara seperti ini, upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat diwujudkan.
(miq/miq)

 2 months ago
27
2 months ago
27