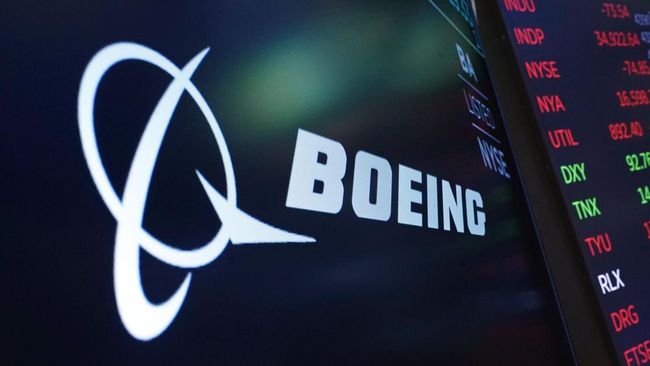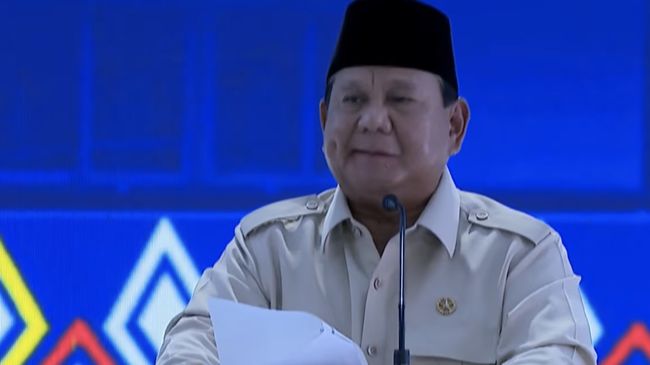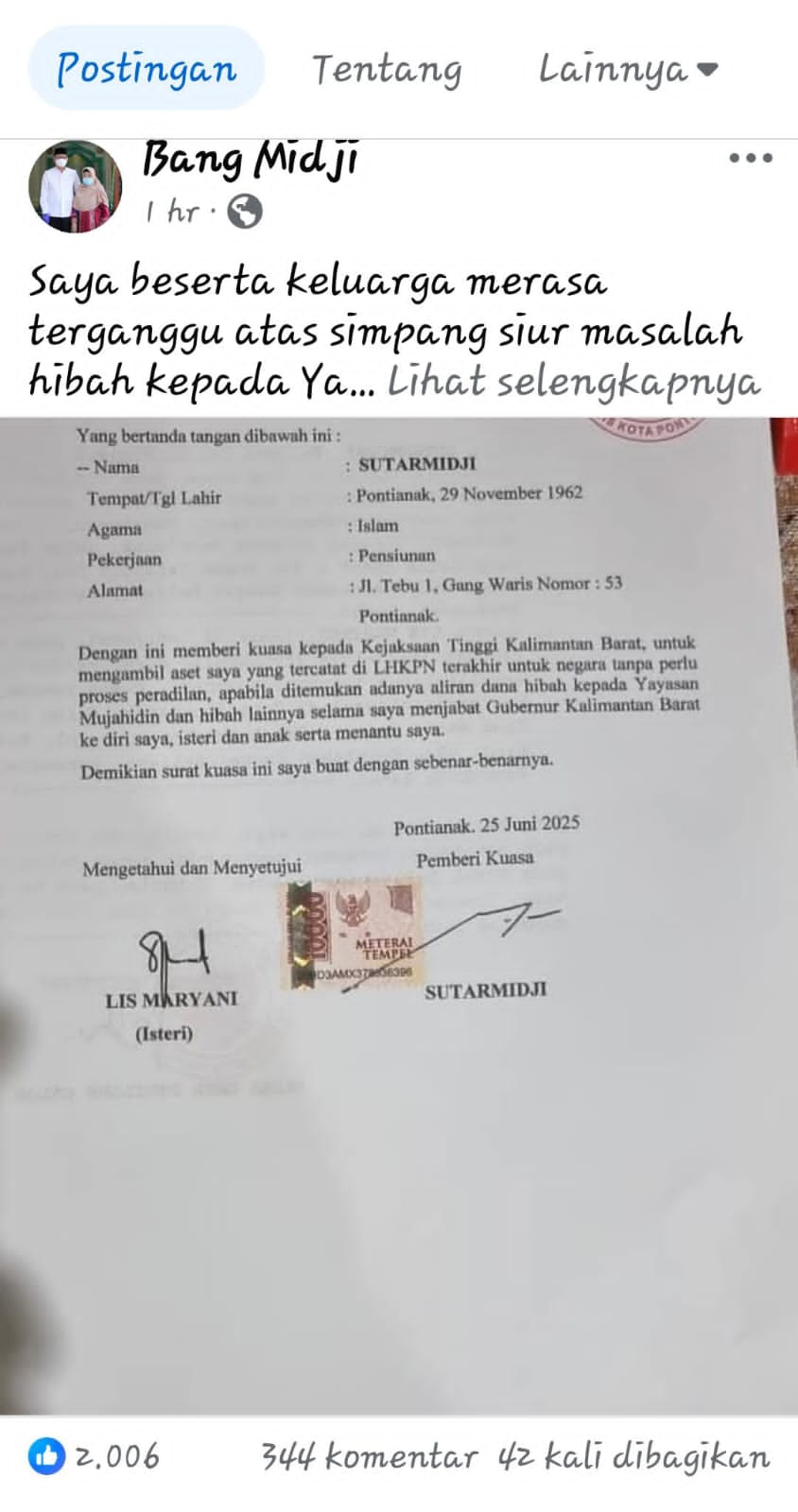Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Laut China Selatan (LCS) bukan hanya sekadar wilayah laut. LCS adalah sebuah teater kompleks di mana narasi keamanan nasional, ambisi ekonomi, dan identitas regional bertabrakan.
Bagi ASEAN, kawasan ini merupakan ujian paling berat bagi sentralitas dan kohesinya. Dinamika yang terjadi merepresentasikan sebuah paradoks yang dalam: upaya bersama untuk "menyejahterakan rakyat ASEAN" justru harus berhadapan dengan realitas "sekuritisasi-desekuritisasi" kebijakan ekonomi negara-negara anggotanya, yang terjerat dalam jaring kebijakan geopolitik organisasi yang saling tumpang-tindih (overlapping).
Proses ini tidak terjadi dalam ruang hampa, tetapi dimediasi melalui mekanisme "minilateralisme" yang pragmatis, sebuah respons terhadap kebuntuan multilateralisme ASEAN. Esai ini akan membedah bagaimana ASEAN dan Negara Anggotanya (AMS) mengelola kepentingan berlapis ini.
Antara menjaga keseimbangan kekuatan eksternal, mempertahankan fungsionalitas organisasi, dan pada akhirnya, mencapai tujuan kesejahteraan kolektif-dari sudut pandang tiga tingkat analisis: ASEAN, ASEAN Member States (AMS), dan lokal.
Konsep "sekuritisasi" yang diperkenalkan oleh Mazhab Kopenhagen (Buzan, et al., 1998) mengacu pada proses di mana sebuah isu diangkat dari ranah politik normal menjadi persoalan keamanan eksistensial, yang memerlukan tindakan luar biasa. Di LCS, China telah berhasil menyekuritisasi klaim historisnya melalui modernisasi militer yang masif dan pembangunan pulau buatan. Namun, respons AMS terhadap hal ini bersifat dualistik, tercermin dalam kebijakan ekonomi mereka.
Di satu sisi, terdapat proses desekuritisasi di tingkat bilateral. Banyak negara anggota ASEAN, meski memiliki sengketa maritim dengan China, secara aktif mengejar integrasi ekonomi dengan raksasa tersebut.
China telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 15 tahun berturut-turut, dengan nilai perdagangan barang mencapai $722 miliar pada kuartal pertama 2024 saja (ASEAN Stats, 2024). Investasi China dalam proyek-proyek infrastruktur seperti Belt and Road Initiative (BRI) di Kamboja, Laos, dan Indonesia, menciptakan ketergantungan ekonomi yang dalam.
Dari sudut pandang nasional AMS, ini adalah kebijakan ekonomi rasional yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat mereka melalui pertumbuhan GDP, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur. Terlebih, bagi banyak elite politik di ASEAN, kerja sama ekonomi dengan China bukanlah pengkhianatan terhadap kedaulatan, tetapi sebuah pragmatisme yang diperlukan untuk pembangunan nasional. (Jones & Smith, 2022, p. 45).
Namun, di sisi lain, proses sekuritisasi terjadi secara simultan. Negara-negara seperti Vietnam dan Filipina terus meningkatkan anggaran pertahanan mereka, dengan fokus besar pada modernisasi angkatan laut. Vietnam, misalnya, telah menerima kapal pemandu rudal canggih dari Jepang dan AS.
Pada tingkat ASEAN, isu LCS selalu dibingkai sebagai ancaman terhadap perdamaian dan stabilitas regional, yakni sebuah bahasa yang mencerminkan sekuritisasi kolektif, meski hati-hati. Kebijakan ekonomi yang mendalam dengan China (desekuritisasi) justru membuat kebutuhan untuk memperkuat kapasitas pertahanan (sekuritisasi) menjadi semakin mendesak, menciptakan dilema keamanan klasik.
ASEAN menghadapi tantangan besar dalam menyelaraskan kebijakan geopolitiknya yang seringkali tumpang-tindih dan tidak konsisten. Di satu sisi, organisasi ini memiliki Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea 2002 dan sedang dalam perundingan panjang untuk sebuah Code of Conduct (COC).
Dokumen-dokumen ini mewakili upaya untuk menciptakan sebuah norma dan kerangka hukum bersama, yang esensinya adalah untuk mendesekuritisasi sengketa melalui dialog dan diplomasi. Namun, efektivitasnya dibatasi oleh prinsip utama ASEAN, yaitu konsensus dan non-interferensi.
Perbedaan kepentingan nasional yang tajam di antara AMS mengenai LCS, terutama dari negara yang memiliki klaim langsung seperti Filipina dan Vietnam, hingga negara yang tidak berkepentingan langsung seperti Laos dan Kamboja-sering memicu kebuntuan.
Insiden pada tahun2012, di mana Kamboja sebagai Chair ASEAN diduga memblokir komunike akhir karena tekanan China, merupakan bukti nyata bagaimana kepentingan geopolitik eksternal dapat memecah belah dan melumpuhkan fungsi kolektif ASEAN (Thayer, 2017).
Overlap atau tumpang tindih ini menciptakan kebijakan yang terfragmentasi. Sementara ASEAN secara kolektif mendorong COC, masing-masing AMS menjalankan diplomasi dan strategi keamanan mereka sendiri, seringkali bertentangan dengan posisi resmi ASEAN. Ini adalah sebuah tightrope walk yang rumit: menjaga keseimbangan kekuatan dengan tidak memihak secara terang-terangan kepada AS atau China, sambil memastikan organisasi tetap relevan dan fungsional.
Guna menghadapi keterbatasan multilateralisme ASEAN, minilateralisme muncul sebagai mekanisme yang semakin populer dan efektif. Minilateralisme merujuk pada kerja sama antara sejumlah kecil negara yang memiliki kepentingan dan kapasitas yang sama untuk menangani isu tertentu.
Di LCS, bentuk minilateralisme ini mengambil berbagai bentuk. Kerja sama segitiga antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia dalam patroli laut bersama di perairan sekitar Pulau Sipadan dan Ligitan adalah contohnya. Yang lebih strategis adalah kemunculan format seperti ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei) yang meski tidak formal, sering melakukan koordinasi tertutup untuk menyelaraskan posisi mereka mengenai COC (Graham, 2023).
Hal yang paling menonjol adalah minilateralisme yang melibatkan kekuatan eksternal. The Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) antara AS, Jepang, Australia, dan India, meski bukan bagian dari ASEAN, memiliki agenda maritim yang jelas yang berdampak langsung pada LCS. Demikian pula, kemitraan AUKUS (Australia, UK, US).
Keberadaan blok-blok ini memaksa ASEAN untuk lebih lincah. Alih-alih menolaknya, beberapa AMS melihatnya sebagai alat untuk menyeimbangkan kekuatan dan, yang terpenting, sebagai sumber investasi alternatif.
Maka, minilateralisme yang melibatkan mitra seperti Jepang dan Australia menawarkan paket yang menarik: kerja sama keamanan maritim dan investasi pada infrastruktur kualitas tinggi, memberikan pilihan kepada AMS untuk mendiversifikasi ketergantungan ekonomi mereka dan pada akhirnya, memperkuat posisi tawar mereka" (Tan, 2021, p. 112).
Dari sudut pandang lokal, minilateralisme yang berfokus pada isu-isu teknis, seperti penelitian kelautan, pencarian dan penyelamatan, penanganan polusi laut, atau penanggulangan penangkapan ikan ilegal yang langsung berkontribusi pada kesejahteraan adalah bagian dari soft power yang dapat dilakukan. Nelayan yang terlindungi, ekosistem laut yang terjaga, dan jalur pelayaran yang aman adalah output nyata yang dirasakan di tingkat akar rumput, harus segera diupayakan.
Soft power ini dapat diperkuat oleh jaring minilateralisme yang pragmatis. Ketika mekanisme ASEAN secara keseluruhan tersendat perbedaan kepentingan, kelompok-kelompok kecil seperti patroli bersama Indonesia-Malaysia-Filipina atau koordinasi informal ASEAN-5 (negara pengeklaim) muncul sebagai solusi. Inilah soft power yang dapat dijadikan aksi, melalui kerja sama teknis di tingkat terbatas yang membangun kepercayaan dan kapasitas tanpa harus menunggu konsensus seluruh anggota.
Bahkan kerja sama segitiga di bidang penanggulangan sampah laut atau penelitian biodiversitas, yang melibatkan ilmuwan dan nelayan, adalah bentuk soft power yang langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat lokal. Mereka tidak hanya mencegah konflik, tetapi juga membangun rasa kepemilikan bersama atas laut. Seperti yang dilakukan di Laut Sulawesi dan bahkan Selat Malaka.
Hal yang sering terlupa adalah bahwa soft power ASEAN juga bersumber dari keberadaan keberagaman budayanya. Pertukaran pelajar, festival budaya maritim, dan kerja sama pariwisata antarnegara anggota dan Mitra dialog menciptakan ikatan sosial yang tahan terhadap gejolak politik.
Jaringan ini adalah semen sosial yang mengingatkan semua pihak bahwa di balik sengketa, ada komunitas yang berbagi sejarah, kuliner, dan cerita yang sama tentang laut. Soft power semacam inilah yang menjadi penyeimbang dari narasi konflik yang kerap dihembuskan dari luar.
Jalan ASEAN untuk menyejahterakan rakyatnya di tengah gejolak LCS adalah sebuah upaya multidimensi yang penuh dengan kompleksitas. Tidak ada solusi tunggal yang mudah. Narasi besar kesejahteraan ekonomi (yang didorong oleh desekuritisasi melalui kerja sama dengan China) harus berhadapan dengan imperatif keamanan nasional (yang memerlukan sekuritisasi dan modernisasi pertahanan).
Fungsionalitas ASEAN diuji oleh overlapping kebijakan geopolitiknya sendiri, yang terpecah antara idealisme unity dan realitas perpecahan akibat kepentingan nasional yang berbeda. Dalam konteks ini, minilateralisme secara internal maupun eksternal, bukanlah pengganti bagi sentralitas ASEAN, melainkan sebuah pelengkap yang pragmatis.
Ia menyediakan jalur yang lebih gesit untuk mencapai kemajuan fungsional, menyeimbangkan kekuatan, dan pada akhirnya, memberikan hasil nyata yang dapat menyejahterakan rakyat.
Masa depan kemaritiman ASEAN akan ditentukan oleh kemampuannya untuk merangkul kerumitan ini. ASEAN harus berreformasi dan menyelaraskan diri dalam menjadi agen konduktor yang lihai, yang mampu mengorkestrasikan simfoni kebijakan yang terdiri dari nada-nada multilateral, minilateral, regional, nasional, dan lokal.
Tujuannya bukan lagi untuk menyelesaikan sengketa secara mutlak, tetapi untuk mengelolanya dengan cukup baik sehingga gelombang geopolitik tidak menenggelamkan tujuan kesejahteraan bersama.
(miq/miq)

 3 months ago
45
3 months ago
45