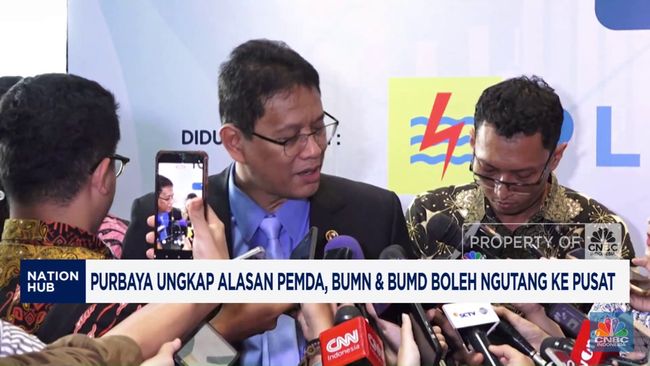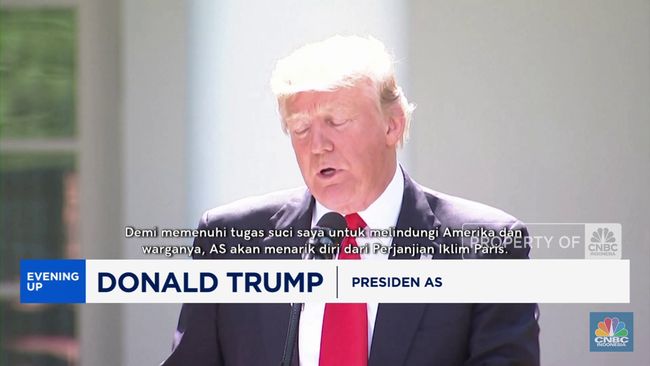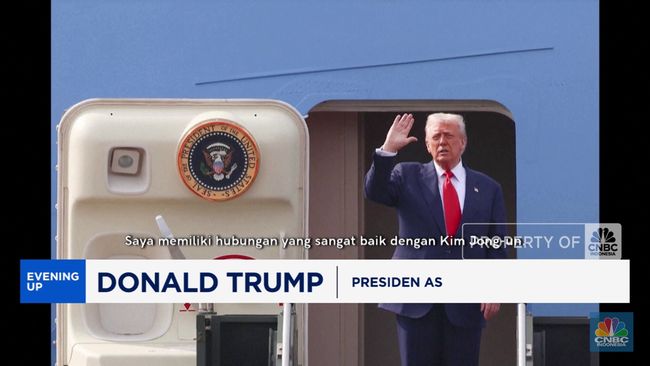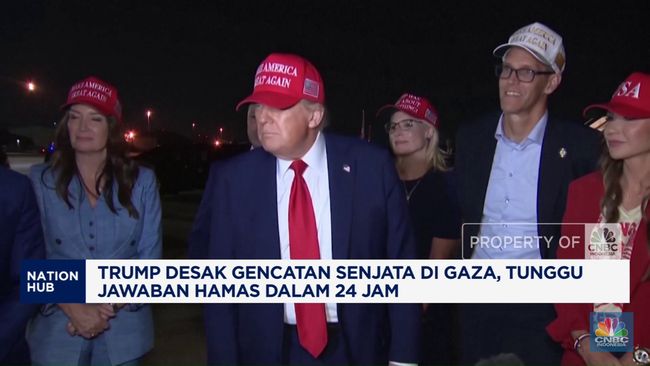Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Konflik bersenjata antara Iran dan Israel yang pecah sejak pertengahan Juni 2025 bukan hanya mengguncang kawasan Timur Tengah, tetapi juga menandai kegagalan sistem keamanan kolektif internasional dalam mencegah eskalasi strategis. Ini adalah tipping point baru dalam geopolitik global yang tidak hanya menguji daya tahan diplomasi multilateral, tetapi juga mengguncang pasar energi dan memperkuat realitas dunia multipolar.
Ketika Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump mempertimbangkan keterlibatan militer langsung, ekspektasi global justru beralih ke China, aktor besar dalam tatanan internasional baru, yang selama ini cenderung menerapkan strategi soft balancing dalam urusan luar negeri. Namun, kali ini Beijing menghadapi dilema besar: apakah tetap menjadi status quo power atau mulai memainkan peran sebagai crisis manager global?
Eskalasi Strategis dan Volatilitas Global
Serangan pre-emptive Israel terhadap instalasi nuklir Iran pada 13 Juni 2025 memicu retaliatory strike berskala besar. Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone hipersonik yang menembus sistem pertahanan berlapis Israel, termasuk Arrow 3 dan Iron Dome. Dalam situasi ini, tercipta fragile balance of power yang sewaktu-waktu dapat runtuh.
Jika AS memutuskan untuk melakukan intervensi militer secara terbuka, maka konflik bilateral akan berubah menjadi multi-theater conflict dengan dampak luas terhadap stabilitas regional dan arsitektur keamanan global. Selain dampak kemanusiaan yang masif, salah satu implikasi paling nyata adalah terganggunya jalur distribusi energi dunia.
Sekitar 20 persen pasokan minyak mentah global melewati Selat Hormuz-chokepoint strategis yang kini berada dalam bayang-bayang blokade Iran. Kenaikan harga Brent hingga mendekati USD 79 per barel dan WTI ke atas USD 77 menunjukkan reaksi pasar terhadap risiko geopolitik ini.
Tidak menutup kemungkinan harga bisa menembus USD 100 jika eskalasi meluas. Kondisi ini mengingatkan pada oil shock pasca-invasi AS ke Irak tahun 2003, yang turut mendorong inflasi dan memaksa bank sentral di berbagai negara mengetatkan kebijakan moneter.
Erosi Rezim Nonproliferasi dan Polarisasi Global
Konflik ini juga mengguncang fondasi rezim nonproliferasi nuklir internasional. Jika Iran keluar dari Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT), bukan hanya kawasan Timur Tengah yang terancam, melainkan juga kredibilitas norma internasional yang dibangun sejak Perang Dingin. Hal ini berpotensi menciptakan security dilemma baru di kawasan lain seperti Asia Selatan dan Semenanjung Korea.
Respons diplomatik dari negara-negara besar pun mulai terlihat. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi BRICS di Rio de Janeiro, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyampaikan bahwa serangan terhadap fasilitas nuklir Iran oleh Israel dan AS melanggar NPT dan Resolusi DK PBB 2231. Pernyataan ini didukung oleh deklarasi bersama BRICS+, yang menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan menyerukan penghentian agresi militer terhadap Iran.
Dukungan ini menjadi diplomatic leverage baru bagi Teheran, sekaligus menunjukkan polarisasi dalam tatanan internasional yang semakin mengarah pada bloc alignment antara negara-negara Global South dengan kekuatan non-Barat seperti China dan Rusia.
China: Dari Hedging ke Leadership?
Dalam lanskap baru ini, Beijing menghadapi ujian kebijakan luar negeri yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Sebagai aktor ekonomi terbesar kedua di dunia, China memiliki strategic stake dalam stabilitas kawasan Teluk. Pada 2024, sekitar 15 persen impor minyak mentah China berasal dari Iran, dan pada saat yang sama, China juga menjalin kemitraan penting dengan Israel dalam bidang infrastruktur dan teknologi.
Namun, kedekatan Beijing dengan Teheran tidak bisa diabaikan. Iran dan China telah menandatangani kemitraan strategis 25 tahun, terlibat aktif dalam Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO), serta mengadakan latihan militer bersama. Sementara itu, Israel tetap menjadi sekutu utama Amerika Serikat di kawasan. Ketimpangan afiliasi geopolitik ini menimbulkan pertanyaan serius tentang sejauh mana China dapat memainkan peran sebagai honest broker.
Meski demikian, rekam jejak diplomasi China mulai menunjukkan ambisi menjadi norm entrepreneur baru di dunia pasca-hegemonik. Keberhasilan Beijing dalam memediasi rekonsiliasi Iran-Arab Saudi pada 2023 telah membuka jalan bagi peran yang lebih proaktif dalam manajemen krisis internasional.
Krisis ini menyentuh Indonesia, tidak hanya sebagai negara dengan keterkaitan ekonomi global, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas Muslim internasional yang memiliki posisi moral dalam isu perdamaian.
Gejolak harga minyak dan potensi gangguan suplai energi akan berdampak pada APBN, stabilitas fiskal, dan tekanan terhadap subsidi energi nasional. Karena itu, Indonesia perlu bersuara lebih aktif dalam forum multilateral seperti OKI dan ASEAN, serta mendorong inclusive peacebuilding framework berbasis diplomasi kolektif.
Kita hidup dalam dunia yang bergerak menuju tatanan multipolar, di mana narasi kekuatan tidak lagi dimonopoli oleh Barat. Dalam situasi ini, menjadi normative actor-negara yang mengedepankan nilai dan perdamaian global-lebih relevan daripada sekadar menjadi pengikut arus besar kekuatan geopolitik.
Krisis Iran-Israel bukan sekadar konflik dua negara, melainkan stress test bagi sistem internasional saat ini, baik dari sisi keamanan, energi, maupun solidaritas global. Dunia sedang menanti apakah China akan tetap bertahan sebagai kekuatan pasif atau naik kelas menjadi constructive power yang mampu menjembatani krisis dan membentuk ulang arsitektur keamanan global.
Bagi Indonesia, ini bukan hanya momen reflektif, tetapi juga ajakan untuk bertindak. Dalam sejarah yang sedang ditulis ulang, menjadi juru damai, meski dalam skala kecil adalah posisi yang jauh lebih bermartabat daripada hanya menjadi penonton diam.
(miq/miq)

 3 months ago
33
3 months ago
33