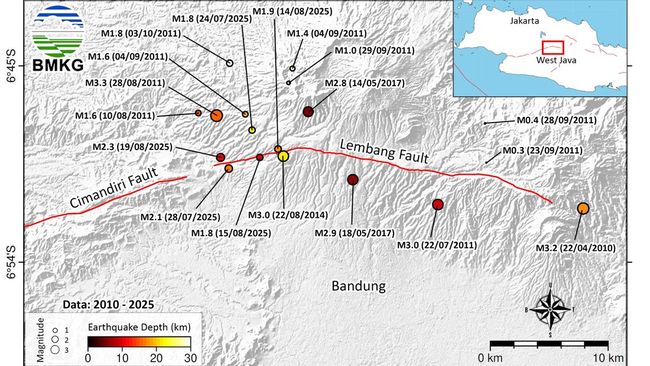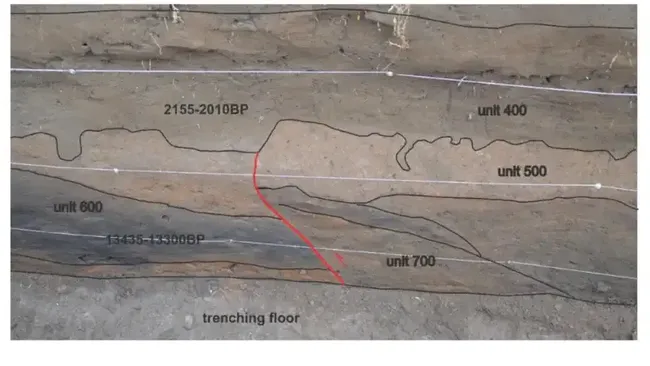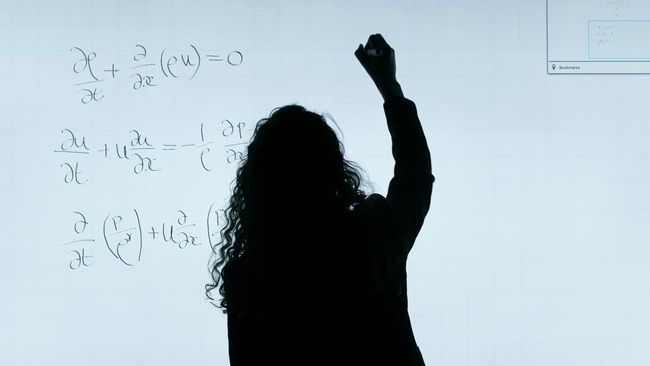Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Tahun 2026 menjadi salah satu tahun yang krusial, setidaknya dalam menyambut arah pembentukan regulasi soal politik ke depan. Sebab, menyongsong tahun 2026 berarti kita harus siap dengan pembahasan soal Revisi UU Kepemiluan Politik yang menjadi agenda Program Legislasi Nasional Prioritas di tahun ini.
Kendati begitu, tulisan ini sejatinya tidak akan membahas mengenai kerangka bangun hukum kepemiluan yang menjadi diskursus oleh pemerintah, DPR, dan internal partai masing-masing seperti pilkada langsung atau melalui DPRD, ambang batas pencalonan Presiden dan ambang batas kursi di DPR, ataupun soal model pemilihan legislatif terbuka, tertutup, ataupun campuran.
Tulisan ini justru akan membahas mengenai sejauh mana revisi UU kepemiluan ini untuk menanggulangi praktik state capture dalam tatanan bernegara ke depannya.
Apa Itu State Capture?
Istilah state capture dewasa ini menjadi pembicaraan hangat dalam diskursus publik. Ia muncul tatkala pembicaraan soal korupsi, pemilu mahal, sampai ke penegakan hukum.
Secara sederhana, state capture dapat dipahami sebagai kondisi ketika proses pengambilan keputusan negara berhasil "dibajak" oleh kepentingan sempit segelintir aktor. Yang ditangkap bukan wilayah, bukan lembaga secara fisik, melainkan arah kebijakan, hukum, dan regulasi.
Negara tetap berdiri, pemilu tetap berlangsung, Parlemen tetap bersidang. Namun, substansi keputusan publik tidak lagi ditentukan oleh kepentingan umum, melainkan oleh mereka yang memiliki sumber daya paling besar untuk memengaruhi negara.
Dalam beberapa kasus, state capture erat kaitannya dengan korupsi. Namun, berbeda dengan korupsi konvensional yang biasanya melibatkan pelanggaran hukum secara terang-terangan, state capture bekerja lebih halus dan sering kali legal secara formal.
Jika korupsi biasa melanggar aturan, state capture justru membentuk aturan. Jika korupsi terjadi setelah kebijakan dibuat, state capture bekerja sebelum kebijakan lahir. Inilah yang membuatnya jauh lebih berbahaya, karena ia merusak fondasi negara hukum dari dalam.
Dampak paling nyata dari state capture adalah erosi demokrasi substantif. Partisipasi publik direduksi menjadi formalitas prosedural.
Pemilu tetap berlangsung, tetapi pilihan kebijakan sesungguhnya telah dipersempit jauh sebelum rakyat memberikan suara. Dalam kondisi ini, demokrasi berjalan tanpa daya korektif yang nyata, sementara ketimpangan ekonomi dan sosial justru kian menganga.
Di bidang hukum, state capture menimbulkan distorsi yang lebih serius. Hukum yang seharusnya menjadi instrumen kepentingan umum bertransformasi menjadi alat kepentingan privat.
Regulasi dibuat dengan celah-celah yang disengaja, sanksi dirancang selektif, dan penegakan hukum diarahkan pada kelompok yang minim daya tawar. Di sinilah kita menyaksikan paradoks negara hukum yang ditandai dengan aturan semakin banyak tetapi rasa keadilan justru semakin langka.
Fenomena ini juga berkaitan erat dengan kecenderungan kriminalisasi yang berlebihan. Ketika negara "ditangkap", hukum pidana berisiko digunakan bukan sebagai ultimum remedium, melainkan sebagai instrumen pengendalian sosial dan politik.
Delik diperluas, sanksi diperberat, tetapi penerapannya timpang. Kelompok lemah berhadapan dengan hukum yang keras, sementara aktor dominan menikmati impunitas struktural.
Pada titik ini, state capture bukan lagi isu abstrak. Ia menjelma dalam kebijakan yang terasa tidak berpihak, hukum yang sulit diakses, dan rasa ketidakadilan yang dialami sehari-hari oleh warga. Negara tidak berhenti bekerja apalagi sampai 'runtuh', tetapi perlahan kehilangan orientasi moral dan konstitusionalnya.
State Capture dan Reformasi Kepemiluan
Pemilu sering dipahami sebagai jantung demokrasi. Melalui pemilu, rakyat menentukan arah kekuasaan, memberi mandat, sekaligus menyediakan mekanisme koreksi terhadap pemerintah.
Selain itu, pemilu juga dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari hak pelestari. Maksudnya, lewat pemilu warga negara dapat melestarikan hak-hak politik dan hak konstitusional lainnya melalui pergantian kekuasaan yang sah dan demokratis.
Maka dari itu, pembentukan regulasi soal kepemiluan justru perlu mendapatkan perhatian lebih. Sebab, alih-alih dapat dijadikan sebagai hak pelestari warga negara, apabila regulasi pemilu disusun tanpa kendali, justru dapat menjadi pelestari state capture itu sendiri.
Salah satu pintu masuk utama state capture dalam pemilu adalah tingginya biaya politik. Pemilu yang mahal mendorong politisi untuk mencari sponsor finansial, sering kali dari kelompok ekonomi berkepentingan.
Ketergantungan ini tidak berhenti setelah pemilu usai. Ia berlanjut dalam bentuk balas jasa kebijakan, perlindungan regulatif, atau pembiaran pelanggaran hukum. Di titik inilah pemilu tidak lagi menjadi mekanisme representasi, melainkan investasi politik dengan ekspektasi keuntungan.
Di sinilah reformasi kepemiluan menjadi isu yang jauh lebih besar dari sekadar teknis pemilu. Ia menyentuh jantung negara hukum dan demokrasi substantif.
Maka dari itu, Reformasi kepemiluan tahun 2026 ini tidak cukup hanya mengatur ulang jadwal, sistem pemungutan suara, atau desain lembaga penyelenggara. Lebih jauh dari pada itu, reformasi kepemiluan seyogianya menyentuh sumber utama state capture seperti pendanaan politik, transparansi proses legislasi, serta konflik kepentingan antara pembuat aturan dan penerima manfaat aturan.
Tentu, amat sangat tidak adil jika semua keterlibatan aktor kuat dalam pemilu langsung dicap sebagai state capture. Bagaimanapun, dalam batas tertentu interaksi antara politik dan ekonomi adalah keniscayaan.
Namun, garis batasnya terletak pada siapa yang diuntungkan secara sistemik dan siapa yang disisihkan. Ketika aturan pemilu secara konsisten mempersempit kompetisi dan mengamankan status quo, di situlah alarm state capture patut dibunyikan.
Reformasi kepemiluan yang berorientasi pada pencegahan state capture mensyaratkan keberanian politik dan tekanan publik. Transparansi pendanaan kampanye, pembatasan biaya pemilu yang efektif, serta penguatan penegakan hukum pemilu bukan sekadar agenda teknokratis.
Ia merupakan langkah untuk mengembalikan pemilu sebagai mekanisme kedaulatan rakyat. Tanpa itu, pemilu berisiko menjadi ritual lima tahunan yang sah secara hukum, tetapi miskin makna demokratis.
Pada akhirnya, pertaruhan reformasi kepemiluan bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah dalam kontestasi politik. Ia adalah soal apakah negara masih mampu menjaga jarak yang sehat dari kepentingan sempit, atau justru semakin larut dalam cengkeraman state capture.
Demokrasi tidak runtuh dalam satu malam. Ia melemah perlahan, ketika pemilu tetap ada, tetapi rakyat semakin jauh dari pusat pengambilan keputusan.
(miq/miq)

 2 hours ago
1
2 hours ago
1