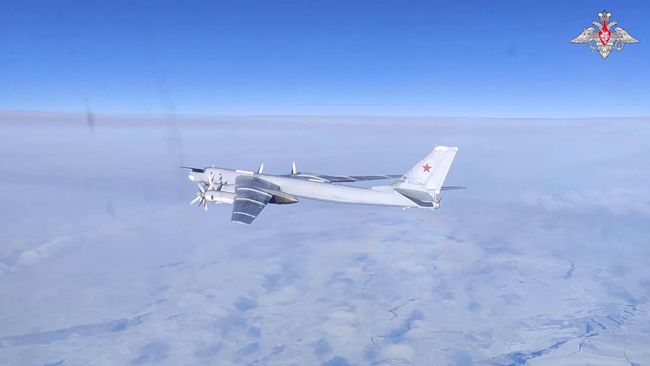Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Artikel ini merupakan serial "Sumitronomics 4.0" yang mengkaji relevansi pemikiran Prof. Sumitro Djojohadikusumo dalam menghadapi dinamika ekonomi kontemporer.
"Pembangunan ekonomi yang hanya memperkaya segelintir orang adalah pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan." Kalimat tajam itu dilontarkan Prof. Sumitro Djojohadikusumo dalam pidatonya tahun 1971 (Djojohadikusumo, 1991). Saat itu, beliau memperingatkan bahaya konsentrasi ekonomi di tangan segelintir konglomerat.
Lima dekade kemudian, peringatan itu bergema kembali, kali ini dalam wujud yang jauh lebih masif. Ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai US$ 130 miliar (2025). Angka yang fantastis. Namun di balik gemerlap angka tersebut, tersembunyi ironi: kekuatan ekonomi digital justru terkonsentrasi di tangan segelintir platform raksasa.
Untuk memahami relevansi peringatan Sumitro dalam konteks hari ini, kita perlu mundur sejenak ke konteks yang memicu keprihatinannya. Pada era 1970-an, ekonomi Indonesia dikuasai oleh 7-8 konglomerat yang mengendalikan sektor-sektor strategis.
Dominasi mereka terbangun lewat kombinasi hubungan politik, akses istimewa ke lembaga keuangan, dan monopoli lisensi. Hasilnya? Pertumbuhan ekonomi tinggi, namun kesejahteraan tidak merata.
Jika dahulu Sumitro mengkhawatirkan dominasi 7-8 konglomerat, realitas hari ini menunjukkan bahwa kita tengah berhadapan dengan 4-5 super-platform digital yang mengendalikan lebih dari 80% transaksi digital di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga ride-hailing.
Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah platform-platform ini tidak hanya menguasai pasar dalam pengertian konvensional, tetapi juga memegang kendali atas infrastruktur informasi, aliran modal, dan akses ke konsumen. Ketiga elemen inilah yang menjadi faktor penentu utama mengenai siapa yang berhak mendapatkan peluang ekonomi dan siapa yang pada akhirnya akan terpinggirkan.
Idealnya, kekhawatiran tersebut tidak perlu muncul karena Indonesia sudah lama memiliki UU Antimonopoli. Masalahnya, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dirancang untuk ekonomi industrial era 2000-an awal, bukan ekonomi digital saat ini.
Karena itu, diperlukan evolusi fundamental dalam cara berpikir tentang antimonopoli. Sudah saatnya diberlakukan "Antimonopoli 4.0"--sebuah framework yang tidak hanya menegakkan aturan setelah pelanggaran terjadi, tetapi merancang ekosistem digital yang secara struktural mendorong persaingan.
Mengapa Monopoli Digital Jauh Lebih Berbahaya
Ada tiga karakteristik fundamental yang membuat monopoli digital jauh lebih powerful dan persisten dibanding monopoli era industrial yang dikhawatirkan Sumitro.
Pertama, efek jaringan. Dalam ekonomi konvensional, perusahaan besar memiliki keunggulan melalui economies of scale di mana biaya per unit turun seiring volume produksi naik. Namun di era digital, muncul fenomena yang secara ekonomi jauh lebih powerful, yaitu efek jaringan.
Nilai sebuah platform meningkat secara non-linear dengan bertambahnya jumlah pengguna, sebuah konsep yang pertama kali diformalkan oleh ekonom Robert Metcalfe. Efek jaringan ini menciptakan dinamika "pemenang-menyapu-semua" (winner-takes-all), di mana pemenang pasar akan terus membesar secara otomatis sementara yang kecil tergilas.
Fenomena ini berbeda secara fundamental dari economies of scale tradisional karena nilainya tumbuh bukan dari efisiensi produksi, melainkan dari penambahan pengguna itu sendiri, menciptakan positive feedback loops yang mengunci pasar (Shapiro & Varian, 1999).
Kedua, ekonomi data. Jika aset terpenting era industrial adalah modal fisik (pabrik, mesin), di era digital aset utamanya adalah data. Bedanya fundamental: modal fisik mengalami diminishing returns, sementara data justru menciptakan increasing returns. Semakin banyak data, semakin akurat prediksi dan personalisasi layanan.
Lebih krusial lagi, data adalah aset non-rivalrous--penggunaan oleh satu pihak tidak mengurangi ketersediaannya untuk lainnya. Platform dengan data dari 100 juta transaksi memiliki keunggulan yang nyaris tak tertandingi oleh pendatang baru, seberapa besar pun modal mereka.
Yang lebih mengkhawatirkan, data ini dikumpulkan dari aktivitas konsumen (mulai dari setiap pencarian, setiap klik, setiap transaksi) namun kepemilikan dan kontrol eksklusif atas data ini berada di tangan platform (privat).
Dari perspektif ekonomi politik, ini analog dengan privatisasi sumber daya alam di mana nilai yang diciptakan secara kolektif diakumulasi secara privat tanpa kompensasi proporsional kepada pencipta nilai tersebut (Posner & Weyl, 2018).
Ketiga, kekuatan intermediary. Platform digital berfungsi sebagai perantara antara supply dan demand, antara merchant dan pembeli, antara driver dan penumpang. Posisi intermediary ini memberikan kekuasaan yang luar biasa untuk menentukan siapa melihat apa, siapa mendapat akses ke peluang ekonomi, dan dengan persyaratan apa.
Kekuasaan ini dieksekusi melalui algoritma yang menentukan ranking, visibilitas, dan harga. Namun algoritma ini adalah kotak hitam dari perspektif publik, tidak transparan, tidak bisa diaudit, dan bisa dimanipulasi untuk kepentingan platform.
Penelitian European Commission (2020) mengungkap beberapa platform e-commerce secara sistematis menurunkan ranking produk dari kompetitor atau merchant kecil sambil menaikkan ranking produk mereka sendiri, praktik yang disebut self-preferencing.
Kombinasi ketiga karakteristik tersebut menciptakan struktur pasar yang secara inheren cenderung ke arah monopoli atau oligopoli ketat. Studi OECD (2022) menunjukkan bahwa concentration ratio empat perusahaan teratas (CR-4) di sektor digital platform rata-rata di atas 75-85%, dibandingkan 40-50% di sektor tradisional.
Ketika UU Antimonopoli Kehilangan Taringnya
UU 5/1999 seperti banyak UU Antimonopoli di berbagai negara menghadapi keterbatasan struktural dalam menghadapi ekonomi digital. Framework antimonopoli konvensional cenderung mengukur dominasi melalui pangsa pasar (market share) dalam batas geografis dan produk yang terdefinisi jelas.
Masalahnya, di pasar digital kekuatan pasar (market power) seringkali jauh melebihi indikasi pangsa pasar formal. Ini karena biaya perpindahan dan biaya menggunakan banyak platform sekaligus menciptakan ketergantungan yang tidak terukur dalam data pangsa pasar.
Merchant kecil secara teoritis bisa berjualan di berbagai platform, namun pada kenyataannya merchant UMKM sering terkunci pada satu atau dua platform karena biaya operasional mengelola inventaris di berbagai platform. Ini adalah ilustrasi sempurna tentang perbedaan antara market share sebagai ukuran formal dan market power sebagai realitas ekonomi.
Teori ekonomi industri modern telah mengakui kompleksitas multi-sided markets di mana platform mempertemukan dua atau lebih kelompok pengguna yang berbeda dan mengenakan harga yang berbeda. Strategi pricing di multi-sided markets bisa tampak predatory dari kacamata framework konvensional, padahal sebenarnya adalah strategi legitimate untuk mencapai critical mass.
Terlebih lagi, platform bisa menggunakan subsidisasi silang antara berbagai lini bisnis. Sebuah platform bisa merugi di e-commerce sambil menghasilkan profit dari fintech atau cloud services, kemudian menggunakan profit tersebut untuk subsidi kompetitif di e-commerce hingga kompetitor keluar pasar. Framework konvensional kesulitan menjawab apakah ini anti-kompetitif karena fokusnya adalah per-pasar, bukan konglomerasi digital.
Hukum antimonopoli konvensional bersifat reaktif karena hanya bertindak setelah ada bukti kerugian konsumen atau keluarnya kompetitor. Pada pasar digital yang bergerak cepat dan bersifat winner-takes-all, pendekatan ini dianggap terlambat. Karena saat sanksi dijatuhkan, struktur pasar biasanya sudah terkunci dan konsumen telah terjebak dalam ekosistem tertutup.
Sejarah kebijakan antimonopoli global menunjukkan bahwa salah satu solusi paling efektif terhadap monopoli adalah pemisahan struktural, namun dalam konteks platform digital konsep ini menjadi rumit karena sifat ekosistem digital yang terintegrasi.
Bagaimana memisahkan marketplace dari layanan logistik atau pembayaran dalam satu ekosistem digital tanpa mengurangi efisiensi yang dihasilkan integrasi tersebut? Tantangan ini mengungkap paradoks antara efisiensi alokatif dan keberlanjutan persaingan.
Antimonopoli 4.0: Merancang Persaingan dari Awal
Menghadapi keterbatasan struktural framework konvensional, kita memerlukan paradigma baru Antimonopoli 4.0. Ini bukan sekadar revisi teknis UU 5/1999, melainkan pergeseran filosofis fundamental dari reactive enforcement yang menindak setelah kerugian terjadi ke proactive ecosystem design yang merancang struktur pasar yang secara inheren kompetitif. Untuk itu ada empat hal yang harus dilakukan.
Pertama, adopsi ex-ante regulation untuk platform bernilai sistemik--yang kegagalannya atau praktik anti-kompetitifnya akan berdampak sistemik pada ekonomi nasional. Konsep ini mirip dengan pengaturan lembaga keuangan (sistemik dalam stabilitas sistem keuangan), namun diterapkan dalam konteks persaingan usaha.
Platform yang memenuhi kriteria sistemik berdasarkan omzet, jumlah pengguna aktif, atau tingkat ketergantungan UMKM perlu dikenai kewajiban kompetisi tertentu sejak awal, tanpa perlu menunggu bukti pelanggaran.
Kedua, terapkan prinsip netralitas platform. Prinsip ini intinya adalah platform yang mengontrol akses ke pasar harus bersikap netral terhadap semua pelaku ekonomi yang menggunakan platform tersebut.
Marketplace tidak boleh mendiskriminasi merchant berdasarkan ukuran atau afiliasi, platform pembayaran tidak boleh memberikan preferensi ke layanan keuangan dalam satu grup usaha, dan platform aplikasi tidak boleh menghalangi interoperabilitas yang wajar dengan layanan pihak ketiga.
Ketiga, bangun interoperabilitas: kemampuan sistem berbeda saling bertukar data dan fungsi. Interoperabilitas mengurangi biaya perpindahan dan mencegah penguncian yang menjadi sumber kekuatan monopoli.
Keempat, wajibkan transparansi algoritmik. Ini bukanlah isu teknis semata, melainkan prasyarat untuk akuntabilitas ekonomi. Transparansi bukan berarti membuka kode sumber yang merupakan rahasia dagang.
Keterbukaan dimaksud adalah tentang parameter umum yang mempengaruhi peringkat dan visibilitas di platform, mekanisme banding yang efektif bagi merchant yang dirugikan oleh keputusan algoritmik, dan kewajiban audit berkala oleh pihak ketiga independen untuk memastikan tidak ada bias sistematis.
Monopoli digital pada dasarnya adalah manifestasi modern dari masalah yang sama yang diingatkan Sumitro lima dekade lalu, konsentrasi kekuatan ekonomi yang menghambat kesempatan bagi sebagian besar rakyat. Teknologi platform seharusnya menjadi alat pemerataan, bukan sarana konsentrasi baru.
Kerangka Antimonopoli 4.0 bukanlah upaya mengekang inovasi atau menghambat pertumbuhan platform digital, melainkan memastikan pertumbuhan digital Indonesia berkelanjutan dan inklusif. Di mana UMKM tumbuh tanpa terkunci dalam ekosistem yang menguras keuntungan mereka. Di mana nilai ekonomi dari data 280 juta penduduk didistribusikan adil.
Pertanyaannya bukan apakah Indonesia membutuhkan Antimonopoli 4.0, melainkan apakah kita memiliki keberanian politik untuk mengimplementasikannya. Tanpa itu, kedaulatan digital hanya slogan kosong. Kita akan tetap menjadi pasar bagi monopoli yang mengorbankan inovasi, kesejahteraan konsumen, dan peluang UMKM demi akumulasi profit para raksasa digital.
Dan itu, seperti yang diingatkan Sumitro lima dekade lalu, adalah pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan.
(miq/miq)

 3 hours ago
1
3 hours ago
1