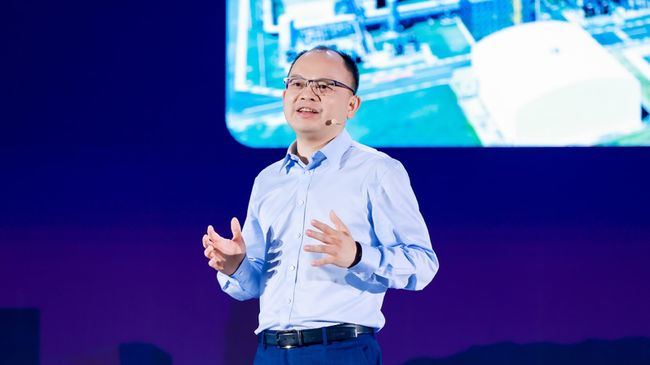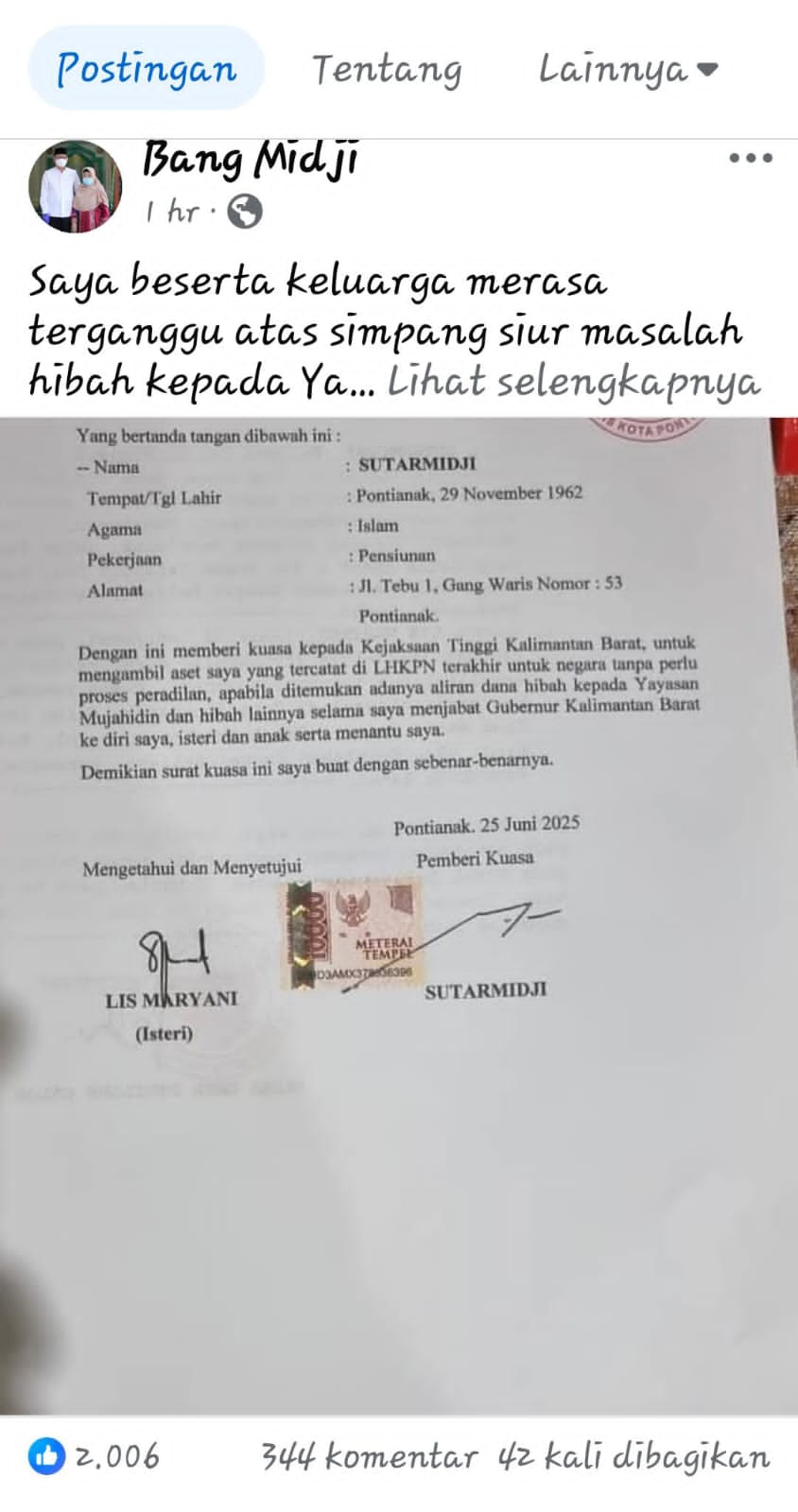Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Artikel ini merupakan bagian dari serial "Sumitronomics 4.0" yang mengkaji relevansi pemikiran Prof. Sumitro Djojohadikusumo dalam menghadapi dinamika ekonomi kontemporer.
Pada tahun 1957, di tengah perdebatan sengit tentang nasionalisasi perusahaan Belanda, Sumitro Djojohadikusumo membuat pernyataan visioner: "Kemerdekaan politik tanpa kemandirian ekonomi adalah kemerdekaan yang rapuh." (Djojohadikusumo, 1991).
Tujuh dekade kemudian, Indonesia menghadapi dilema struktural serupa dalam bentuk baru. Kali ini, yang dipertaruhkan bukan kilang minyak atau perkebunan karet, melainkan aset strategis abad ke-21: data pribadi 280 juta penduduk, algoritma yang membentuk perilaku ekonomi, serta infrastruktur digital yang menopang hampir seluruh aktivitas produktif.
Pertanyaan fundamentalnya tetap sama: apakah Indonesia akan menjadi principal dalam ekonomi digital, atau sekadar agent bagi platform asing yang mengekstraksi nilai tanpa kontribusi proporsional?
Ancaman Kolonialisme Digital
Ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai US$ 130 miliar pada tahun 2025, terbesar di Asia Tenggara. Namun, di balik angka megah ini menyembunyikan realitas pahit: besarnya transaksi tidak otomatis mencerminkan nilai tambah domestik atau kendali ekonomi nasional.
Struktur pasar digital Indonesia menunjukkan konsentrasi yang mengkhawatirkan. Di e-commerce, pemain utama seperti Shopee dan Tokopedia berada di bawah kendali strategis entitas asing.
Di ride-hailing, Grab mendominasi kawasan, sementara Gojek memiliki struktur kepemilikan campuran dengan porsi asing signifikan. Media sosial dan periklanan digital nyaris sepenuhnya dikuasai Meta, Google, dan TikTok.
Di sisi lain, studi OECD (2023) mengungkap realitas getir dalam arsitektur pajak global: sekitar 37,1% dari laba global perusahaan multinasional--setara US$ 2,4 triliun--masih dikenakan tarif pajak efektif di bawah 15%. Melalui praktik profit shifting ke tax havens, perusahaan digital raksasa secara sistematis mengerosi basis pajak domestik.
McKinsey Global Institute (2019) memperkirakan sebagian besar nilai ekonomi digital mengalir ke luar negeri dalam bentuk repatriasi laba, biaya lisensi teknologi, dan komisi platform. Sebuah ekstraksi rente masif yang strukturnya mirip dengan ekstraksi sumber daya alam di era kolonial, hanya yang kini diekstraksi adalah data dan surplus konsumen digital.
Shoshana Zuboff dalam "The Age of Surveillance Capitalism" (2019) mengingatkan bahwa data pribadi telah menjadi komoditas paling berharga dalam ekonomi digital. Seharusnya aset ini dikelola sebagai sumber daya bersama (commons) dengan tata kelola adil, bukan diambil alih secara privat tanpa kompensasi memadai.
Bayangkan, platform seperti Google dan Facebook menghasilkan triliunan rupiah dari data perilaku pengguna Indonesia, namun Indonesia tidak memiliki kontrol regulatori efektif atau mekanisme untuk mendapatkan bagian adil dari nilai yang diciptakan. Ini adalah kegagalan kebijakan fundamental.
Begitu pun dengan masalah ketergantungan pada infrastruktur asing. Ini menciptakan kerentanan sistemik yang berbahaya. Lebih dari 70% traffic internet Indonesia melewati kabel serat optik bawah laut yang sebagian besar dimiliki atau dioperasikan konsorsium internasional--risiko geopolitik yang belum ditangani memadai dalam perencanaan infrastruktur nasional.
Di sektor cloud computing, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, dan Alibaba Cloud mendominasi. Lebih dari 65% beban komputasi di Indonesia berjalan di infrastruktur asing, menciptakan single point of failure berbahaya jika terjadi konflik geopolitik atau sanksi ekonomi.
Data BSSN (2025) menunjukkan lebih dari separuh serangan siber di Indonesia tidak terdeteksi karena keterbatasan kapasitas teknis dan institusional. Tanpa kemampuan melindungi data dan sistem digital dari intrusi, manipulasi, atau sabotase, kedaulatan digital tidak bermakna secara operasional. Ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan isu keamanan nasional yang memerlukan pendekatan whole-of-government.
Membangun Fondasi Kedaulatan Digital
Untuk memutus belenggu ketergantungan digital, diperlukan pendekatan komprehensif dan terstruktur. Kerangka DAI (Distinctive, Adaptive, Inclusive) yang diajukan Dany Amrul Ichdan dalam "Indonesia Naik Kelas" (2025) menawarkan paradigma holistik sebagai landasan kebijakan transformatif.
Perlu digarisbawahi, kedaulatan digital dalam konteks ini bukan berarti isolasi atau proteksionisme sempit, melainkan kedaulatan strategis: kapasitas institusional untuk menetapkan aturan di pasar digital domestik, mengontrol aset strategis, dan memastikan Indonesia mendapat bagian adil dari nilai ekonomi yang diciptakan.
Pertama, distinctive: tata kelola data yang khas. Prinsip distinctive menuntut arsitektur tata kelola data yang sesuai dengan karakteristik khas Indonesia--bukan meniru model Silicon Valley atau regulasi Eropa secara mentah. Indonesia memiliki posisi unik: populasi 280 juta (pasar digital terbesar keempat dunia), lebih dari 700 bahasa daerah, geografi kepulauan kompleks, dan struktur ekonomi heterogen.
Kerangka tata kelola data perlu melampaui PP 71/2019 yang ada. Diperlukan sintesis strategis dari GDPR Eropa yang menekankan individual property rights dan Data Protection Act India yang menekankan data localization. Lebih radikal lagi adalah konsep National Data Trust ala Mariana Mazzucato (2022)--institusi publik yang mengelola data sebagai commons dengan tata kelola yang memastikan kompensasi adil, akses terbuka untuk inovasi, dan redistribusi manfaat inklusif.
Estonia memberikan bukti empiris bahwa model ini layak dan efektif. Melalui X-Road, platform digital yang memungkinkan pertukaran data antar-institusi dengan persetujuan eksplisit dan perlindungan kriptografis. Estonia berhasil menciptakan ekosistem digital yang aman, efisien, dan memberikan kendali kepada warga negara atas data pribadi mereka.
Kedua, adaptive: infrastruktur yang tangguh. Sifat adaptif berarti membangun infrastruktur dan institusi yang tangguh terhadap gangguan teknologi dan gejolak geopolitik. Ini memerlukan investasi publik substansial dalam digital public infrastructure--bukan untuk bersaing langsung dengan platform swasta, melainkan sebagai fondasi yang menurunkan barriers to entry dan mendorong persaingan sehat.
India Stack memberikan contoh inspiratif. Terdiri dari identitas digital (Aadhaar), sistem pembayaran terbuka (UPI), dan kerangka pertukaran data, India Stack berhasil meningkatkan inklusi keuangan dari 35% menjadi 80% dalam lima tahun. Indonesia perlu mengembangkan QRIS menjadi sistem pembayaran nasional yang sepenuhnya interoperabel, didukung sovereign cloud untuk sektor-sektor strategis.
Selain itu, keamanan siber harus diposisikan sebagai pilar pertahanan kedaulatan, yang diperkuat melalui National Cyber Range sebagai kawah candradimuka simulasi krisis, serta adopsi Post-Quantum Cryptography untuk membentengi rahasia negara dari ancaman komputasi masa depan. Ini bukan sekadar belanja teknologi, melainkan "premi asuransi" atas keberlangsungan negara di ruang digital.
Ketiga, inclusive: demokratisasi manfaat digital. Prinsip inklusif dalam ekonomi digital berarti memastikan bahwa manfaat digitalisasi tersebar luas, tidak terkonsentrasi pada segelintir platform besar atau elit urban. Ini bukan hanya imperatif moral, melainkan juga kebutuhan ekonomi (economic necessity).
Karena itu, UMKM tidak boleh hanya menjadi penonton atau sekedar lampiran dalam ekonomi digital, melainkan harus diintegrasikan ke dalam digital value chains dengan akses memadai ke teknologi, kapabilitas, dan pasar. Namun, inklusivitas tidak terjadi otomatis melalui mekanisme pasar. Tanpa intervensi kebijakan tepat, digitalisasi justru memperparah ketimpangan melalui dinamika winner-take-all yang intrinsik dalam ekonomi platform.
Perlu digarisbawahi, network effects dan economies of scale menciptakan kecenderungan monopoli alami, di mana platform mapan dengan basis pengguna besar memiliki keunggulan yang sulit ditandingi. Ini memerlukan kebijakan persaingan yang tegas--bukan untuk melindungi kompetitor yang tidak efisien, melainkan untuk melindungi proses kompetisi itu sendiri (protecting competition, not competitors).
Tiga Pilar Strategis
Indonesia berada di titik kritis. Bonus demografi akan mencapai puncak pada 2030, setelah itu kesempatan emas akan tertutup permanen. Diperlukan tiga pilar kebijakan strategis agar Indonesia mendapat manfaat optimal dari ekonomi digital.
Pertama, reformasi regulasi dan keadilan fiskal. Indonesia harus berani mengambil posisi tegas dalam negosiasi global. Jika kesepakatan Pillar One--bagian dari kesepakatan pajak global untuk mengatasi tantangan pajak di era digital--terus tertunda, Indonesia tidak boleh ragu menerapkan Digital Services Tax (DST) mandiri sebesar 2-3% sebagai tindakan darurat (interim measures).
Ini bukan sekadar mencari pendapatan, melainkan instrumen kedaulatan untuk memastikan nilai ekonomi yang diekstraksi dari 280 juta penduduk kita tidak menguap tanpa kontribusi fiskal yang adil. Sejalan dengan itu, kewajiban lokalisasi data harus ditegakkan secara konsisten guna memastikan aset data nasional berada dalam kendali yurisdiksi Indonesia, sebagaimana praktik yang diterapkan di Uni Eropa maupun China.
Kedua, infrastruktur publik dan resiliensi digital. Indonesia perlu meluncurkan Indonesia Digital Public Infrastructure Initiative sebagai investasi produktif jangka panjang. Kunci keberhasilannya terletak pada pembentukan lembaga profesional independen untuk mengelola sistem pembayaran nasional yang interoperabel dan berstandar global.
Selain itu, pembangunan Sovereign Cloud untuk sektor strategis--seperti perbankan, energi, dan pertahanan--adalah keharusan sebagai "premi asuransi" terhadap risiko geopolitik. Infrastruktur fisik, mulai dari kabel laut hingga pusat data, wajib memiliki kepemilikan mayoritas domestik guna menjamin resiliensi dan konektivitas nasional yang mandiri.
Ketiga, akselerasi teknologi dan kapabilitas domestik. Melalui National AI Mission, Indonesia harus fokus pada aplikasi praktis yang berdampak langsung, misalnya pada sektor prioritas seperti pertanian, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah harus hadir sebagai "pelanggan pertama" melalui kebijakan pengadaan publik untuk solusi digital karya anak bangsa.
Namun, lompatan teknologi ini mustahil tanpa reformasi pendidikan STEM yang radikal untuk menciptakan universitas teknologi kelas dunia. Dukungan kebijakan harus diarahkan pada ekosistem venture capital yang berfokus pada deep tech--bukan sekadar konsumsi--agar inovasi teknologi masa depan lahir dan berakar di tanah air, sekaligus menjadi pemain global.
Keberanian untuk Berdaulat
Visi Sumitro tentang kemandirian ekonomi di abad ke-21 harus diterjemahkan sebagai kedaulatan digital. Seperti beliau memperjuangkan nasionalisasi perusahaan asing di tahun 1950-an untuk kedaulatan ekonomi, kini Indonesia harus memperjuangkan kendali atas data, algoritma, dan infrastruktur digital.
Ini bukan tentang xenofobia atau isolasionisme. Platform asing tetap bisa beroperasi di Indonesia--tetapi dengan aturan yang adil: bayar pajak proporsional, simpan data di Indonesia, transfer teknologi, dan berkontribusi pada ekosistem lokal. Ini adalah strategic sovereignty: kemampuan untuk menentukan nasib sendiri di era digital.
Pertanyaannya bukan apakah Indonesia mampu membangun kedaulatan digital, tetapi apakah kita punya keberanian politik untuk melakukannya. Sumitro berani mengambil keputusan kontroversial di zamannya demi kepentingan jangka panjang bangsa. Kini, giliran kita untuk menunjukkan keberanian yang sama atau kita akan menjadi koloni digital selamanya.

 2 hours ago
2
2 hours ago
2