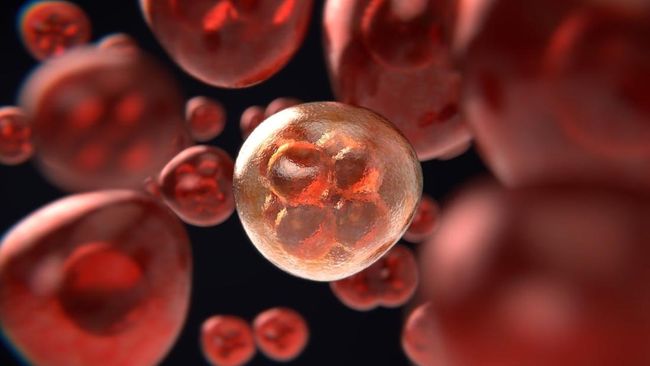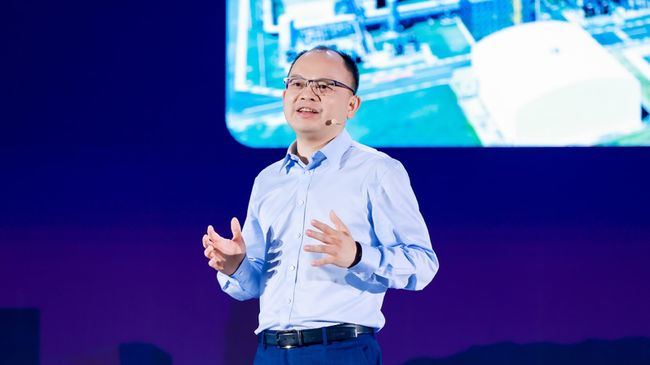Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Artikel ini merupakan bagian dari serial "Sumitronomics 4.0" yang mengkaji relevansi pemikiran Prof. Sumitro Djojohadikusumo dalam menghadapi dinamika ekonomi kontemporer.
Dalam dua artikel sebelumnya, kita telah membahas bagaimana prinsip-prinsip inti Sumitronomics tetap relevan di era digital (CNBC Indonesia, 2/1/2026) dan bagaimana negara perlu berevolusi menjadi adaptive state yang gesit (CNBC Indonesia, 7/1/2026). Pertanyaan kritis kini: di tengah polarisasi ideologi ekonomi global, di mana posisi Sumitronomics 4.0?
Pada kuliah perdana di Universitas Terbuka yang disiarkan TVRI dan RRI, 4 September 1984, Sumitro dalam membahas "Trilogi Pembangunan dan Ekonomi Pancasila" menekankan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi budak teori ekonomi dari manapun, tetapi juga tidak boleh naif menolak semua yang datang dari luar hanya karena sentimen nasionalisme sempit (Djojohadikusumo, 1985).
Pernyataan tersebut mencerminkan posisi unik Sumitro--seorang ekonom yang pernah belajar di Sorbonne dan Rotterdam, namun menolak dogma baik dari kiri maupun kanan spektrum ideologi ekonomi.
Saat ini, empat dekade kemudian Indonesia (masih) terjebak dalam dikotomi serupa. Di satu sisi, ada tekanan mengadopsi agenda neoliberal: liberalisasi total, privatisasi BUMN, deregulasi tanpa batas. Di sisi lain, muncul gelombang populisme ekonomi yang menawarkan proteksionisme ekstrem, nasionalisasi aset asing, dan penutupan diri dari ekonomi global.
Kedua ekstrem ini sama berbahayanya. Neoliberalisme yang tidak terkendali telah memperlebar ketimpangan dan menciptakan krisis finansial berulang (Piketty, 2014). Sementara populisme ekonomi yang reaktif cenderung menghasilkan kebijakan yang tidak berkelanjutan secara fiskal dan mengisolasi negara dari rantai nilai global (Rodrik, 2018).
Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan jalan ketiga--sebuah pendekatan yang mengakui pentingnya pasar dan integrasi global, namun dengan peran negara yang strategis dan komitmen pada pemerataan. Inilah esensi Sumitronomics 4.0: pragmatisme yang tidak terjebak ideologi, namun tetap berpegang pada prinsip bahwa ekonomi harus melayani rakyat banyak.
Pelajaran Pahit dari Dua Ekstrem
Untuk memahami mengapa jalan ketiga diperlukan, kita perlu melihat bagaimana dua ekstrem ideologi ekonomi telah gagal memberikan hasil yang dijanjikan.
Sejak tahun 1980-an, resep neoliberal--yang dipopulerkan melalui Washington Consensus--menjadi dogma dominan (Williamson, 1990). Resepnya sederhana: liberalisasi perdagangan, deregulasi pasar keuangan, privatisasi BUMN, dan meminimalkan peran negara. Hasilnya dijanjikan akan menciptakan pertumbuhan yang "menetes ke bawah" mengangkat semua orang dari kemiskinan.
Realitasnya jauh dari janji. Data OECD (2021) menunjukkan bahwa selama periode 1980-2020, meskipun PDB global meningkat signifikan, ketimpangan pendapatan di hampir semua negara maju justru melebar.
Di Amerika Serikat, sebanyak 1% orang terkaya menguasai 40% kekayaan nasional, sementara upah riil pekerja median stagnan selama empat dekade (Saez & Zucman, 2019). Karena itu, benar kata Piketty (2014) bahwa kapitalisme tanpa intervensi negara cenderung menghasilkan akumulasi kekayaan yang tidak merata--karena return on capital lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi.
Indonesia mengalami fenomena serupa. Reformasi ekonomi pascakrisis tahun 1998 membawa banyak elemen neoliberal: liberalisasi sektor keuangan, pengurangan subsidi, privatisasi BUMN. Hasilnya?
Pertumbuhan ekonomi memang pulih rata-rata 5-6% per tahun sejak 2000, tetapi koefisien gini meningkat dari 0,30 di awal 2000-an menjadi 0,41 pada 2015, sebelum turun bertahap menjadi 0,375 pada Maret 2025. Laporan World Bank (2016) menunjukkan bahwa 10% orang terkaya di Indonesia menguasai sekitar 77% total kekayaan nasional.
Sebagai reaksi terhadap kegagalan neoliberalisme, muncul gelombang populisme ekonomi--dari Brexit, kebijakan "America First" di era Trump, hingga eksperimen ekonomi di Argentina dan Venezuela. Narasi populisme ekonomi menarik secara emosional: melindungi rakyat dari eksploitasi korporasi asing, menasionalisasi sumber daya alam, dan memberikan subsidi besar-besaran.
Namun, track record-nya sering mengecewakan. Venezuela memberikan pelajaran paling ekstrem: nasionalisasi industri minyak dan kebijakan subsidi masif di era Chavez awalnya populer, tetapi berujung pada hiperinflasi yang mencapai ratusan ribu persen pada 2018 dan kontraksi ekonomi sekitar 75% dalam satu dekade (IMF, 2019). Argentina mengalami siklus default utang berulang karena kebijakan fiskal yang tidak berkelanjutan dan isolasi dari pasar global (Reinhart & Rogoff, 2009).
Di Indonesia, kebijakan subsidi BBM yang masif--mencapai Rp 211,87 triliun (realisasi) atau sekitar 2,6% PDB di tahun 2012--menggerogoti anggaran untuk pendidikan dan infrastruktur (Kementerian Keuangan, 2013). Ironisnya, subsidi ini bersifat regresif, di mana 40% manfaatnya dinikmati oleh 20% orang terkaya yang memiliki kendaraan pribadi (World Bank, 2014).
Karena itu, tidak berlebihan bila Dani Rodrik (2018) mengingatkan bahwa populisme ekonomi sering mengabaikan fundamental ekonomi: keberlanjutan fiskal, produktivitas, dan integrasi dengan ekonomi global. Hasilnya adalah solusi jangka pendek yang populer secara politis, namun menciptakan bencana jangka panjang.
Perlu digarisbawahi, baik neoliberalisme maupun populisme ekonomi memiliki satu kelemahan mendasar. Keduanya ideology-driven, bukan evidence-based. Neoliberalisme percaya bahwa pasar selalu benar dan negara selalu salah. Populisme ekonomi percaya bahwa negara selalu benar dan pasar (terutama asing) selalu salah. Keduanya mengabaikan kompleksitas ekonomi modern yang membutuhkan sintesis cerdas antara peran negara dan mekanisme pasar.
Empat Pilar Sintesis Sumitronomics 4.0
Jalan ketiga yang ditawarkan Sumitronomics 4.0 bukanlah kompromi lemah, melainkan sintesis yang mengambil elemen terbaik dari berbagai aliran pemikiran ekonomi, diuji dengan data dan bukti empiris, dan disesuaikan dengan konteks Indonesia. Ada empat pilar utama.
Pertama, negara sebagai market-shaper. Sumitronomics 4.0 menolak baik peran negara yang terlalu kecil (neoliberal) maupun terlalu besar (sosialis). Negara harus menjadi "market-shaper"--pembentuk kondisi pasar yang sehat, kompetitif, dan inklusif (Mazzucato, 2018).
Karena itu, negara harus aktif dalam tiga peran: 1) membangun infrastruktur dasar (baik infrastruktur fisik maupun digital publik--seperti QRIS); 2) menciptakan dan menegakkan aturan main yang memastikan persaingan sehat (regulasi antimonopoli, perlindungan konsumen, standar lingkungan); dan 3) melakukan investasi strategis di sektor dengan eksternalitas tinggi seperti riset dasar, pendidikan, dan teknologi hijau.
Studi World Bank (2019) menunjukkan bahwa setiap 1% peningkatan investasi infrastruktur dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 0,5%.
Kedua, integrasi selektif dengan ekonomi global. Sumitronomics 4.0 menolak baik globalisasi tanpa syarat maupun proteksionisme ekstrem. Yang dibutuhkan adalah "strategic openness"--keterbukaan selektif yang memaksimalkan manfaat integrasi global sambil melindungi sektor-sektor strategis dan rentan.
Korea Selatan sudah memberikan contoh. Negeri ginseng tersebut membuka diri pada ekspor dan investasi asing (FDI) di sektor tertentu, sambil melindungi industri infant dalam periode tertentu dan membangun kapasitas domestik (Chang, 2002). Hasilnya? Dalam 50 tahun, Korea berubah dari negara agraris miskin menjadi ekonomi industri maju dengan Samsung, Hyundai, dan LG yang sanggup berkompetisi di pasar global.
Indonesia perlu menerapkan prinsip serupa di era digital, yaitu membuka pasar untuk investasi asing di sektor teknologi, tetapi dengan persyaratan transfer teknologi, pengembangan talenta lokal, dan pembayaran pajak yang adil. Data menunjukkan bahwa negara-negara dengan kebijakan FDI yang selektif memiliki spillover effect lebih besar (Javorcik, 2004).
Ketiga, predistribusi, bukan hanya redistribusi. Populisme ekonomi cenderung fokus pada redistribusi: pajak orang kaya untuk subsidi orang miskin. Ini penting, tetapi tidak cukup. Sumitronomics 4.0 menekankan "predistribusi"--menciptakan struktur ekonomi yang dari awal mencegah konsentrasi kekayaan berlebihan (Hacker, 2011).
Ini termasuk: pendidikan berkualitas untuk semua, akses ke modal untuk UMKM, regulasi upah yang adil, dan kepemilikan saham karyawan di perusahaan besar. Studi menunjukkan bahwa negara dengan sistem predistribusi yang kuat memiliki ketimpangan lebih rendah tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi (Atkinson, 2015).
Keempat, pragmatisme berbasis bukti. Sumitro terkenal sering mengubah kebijakannya ketika data menunjukkan pendekatan sebelumnya tidak efektif, alias tidak terjebak mazhab atau idiologi tertentu. Yang penting adalah: apa yang terbaik dan bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Sumitronomics 4.0 menerapkan prinsip "experimentation and evaluation"--kebijakan diuji dalam skala kecil, dievaluasi dengan ketat, dan baru diskalakan jika terbukti efektif (Banerjee & Duflo, 2019).
Dari Konsep ke Kebijakan Konkret
Sumitronomics 4.0 harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret. Berikut beberapa rekomendasi implementasi di konteks Indonesia saat ini.
Pertama, reformasi fiskal cerdas. Indonesia perlu meningkatkan tax ratio (menjadi minimal 15% ari PDB). Namun bukan dengan cara populis atau neoliberal, melainkan sistem pajak yang progresif namun pro-growth.
Antara lain berupa pajak digital service untuk platform asing, carbon tax untuk industri pencemar dengan revenue-nya untuk transisi hijau, pajak kekayaan untuk ultra-wealthy (top 0,1%) untuk mendanai infrastruktur pendidikan, dan insentif pajak untuk perusahaan yang reinvestasi di R&D dan pelatihan pekerja.
Kedua, industrial policy yang strategis, bukan proteksionisme buta. Pelajaran dari hilirisasi nikel menunjukkan pentingnya persiapan matang: infrastruktur energi, regulasi lingkungan, pengembangan SDM, dan pasar ekspor harus disiapkan sebelum melarang ekspor bahan mentah.
Framework "mission-oriented innovation policy" bisa diadopsi (Mazzucato, 2018): identifikasi misi nasional (misalnya: menjadi hub produksi baterai EV di Asia Tenggara), lalu koordinasikan investasi publik-swasta, R&D, regulasi, dan pendidikan untuk mencapai misi tersebut.
Ketiga, jaring pengaman sosial yang adaptif. Mengganti subsidi BBM yang tidak tertarget dengan sistem perlindungan sosial yang responsif terhadap data. Ketika harga pangan naik atau terjadi shock ekonomi, bantuan langsung tunai bisa ditransfer dalam hitungan hari ke keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Brasil menunjukkan keberhasilan program Bolsa Família yang menggunakan conditional cash transfer berbasis data untuk mengurangi kemiskinan ekstrem hingga 50% dalam 15 tahun (Soares dkk, 2010).
Keempat, demokratisasi kapital. Alih-alih hanya mengandalkan pajak untuk redistribusi, ciptakan mekanisme agar pekerja dan masyarakat luas memiliki aset produktif. Hal ini bisa dengan cara employee stock ownership plans (ESOP) untuk perusahaan besar, sovereign wealth fund yang dividen-nya dibagikan ke warga (model Alaska Permanent Fund), dan koperasi digital yang dimiliki anggotanya.
Studi menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan karyawan yang signifikan memiliki produktivitas lebih tinggi dan ketimpangan lebih rendah (Blasi dkk, 2013).
Jelaslah, bahwa jalan ketiga Sumitronomics 4.0 adalah posisi yang tegas: menolak dogma neoliberal yang menyerahkan semua pada pasar, menolak populisme ekonomi yang reaktif dan tidak berkelanjutan, dan mengadopsi pragmatisme berbasis bukti yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama.
Sumitro mengajarkan satu pelajaran penting: kejujuran intelektual untuk mengakui bahwa tidak ada satu resep yang cocok untuk semua konteks, dan keberanian untuk bereksperimen dan belajar dari kesalahan. Di era digital yang penuh ketidakpastian ini, pragmatisme yang berprinsip justru lebih dibutuhkan daripada ideologi yang kaku.
Pertanyaannya bukan apakah Indonesia memilih pasar atau negara, terbuka atau tertutup, growth atau equity. Pertanyaan yang tepat adalah: bagaimana kita merancang kombinasi cerdas dari semua elemen ini untuk mencapai tujuan bernegara--kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Itulah esensi jalan ketiga Sumitronomics 4.0.
(miq/miq)

 16 hours ago
4
16 hours ago
4