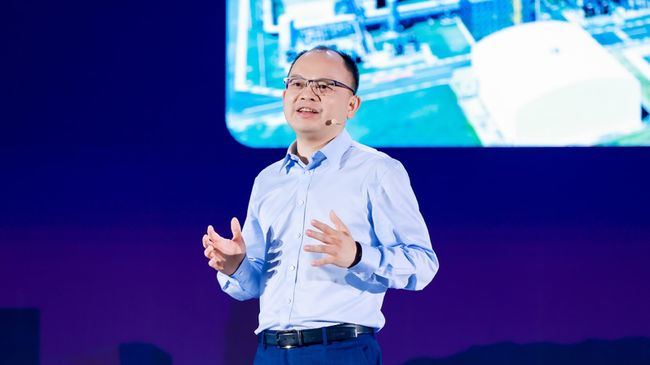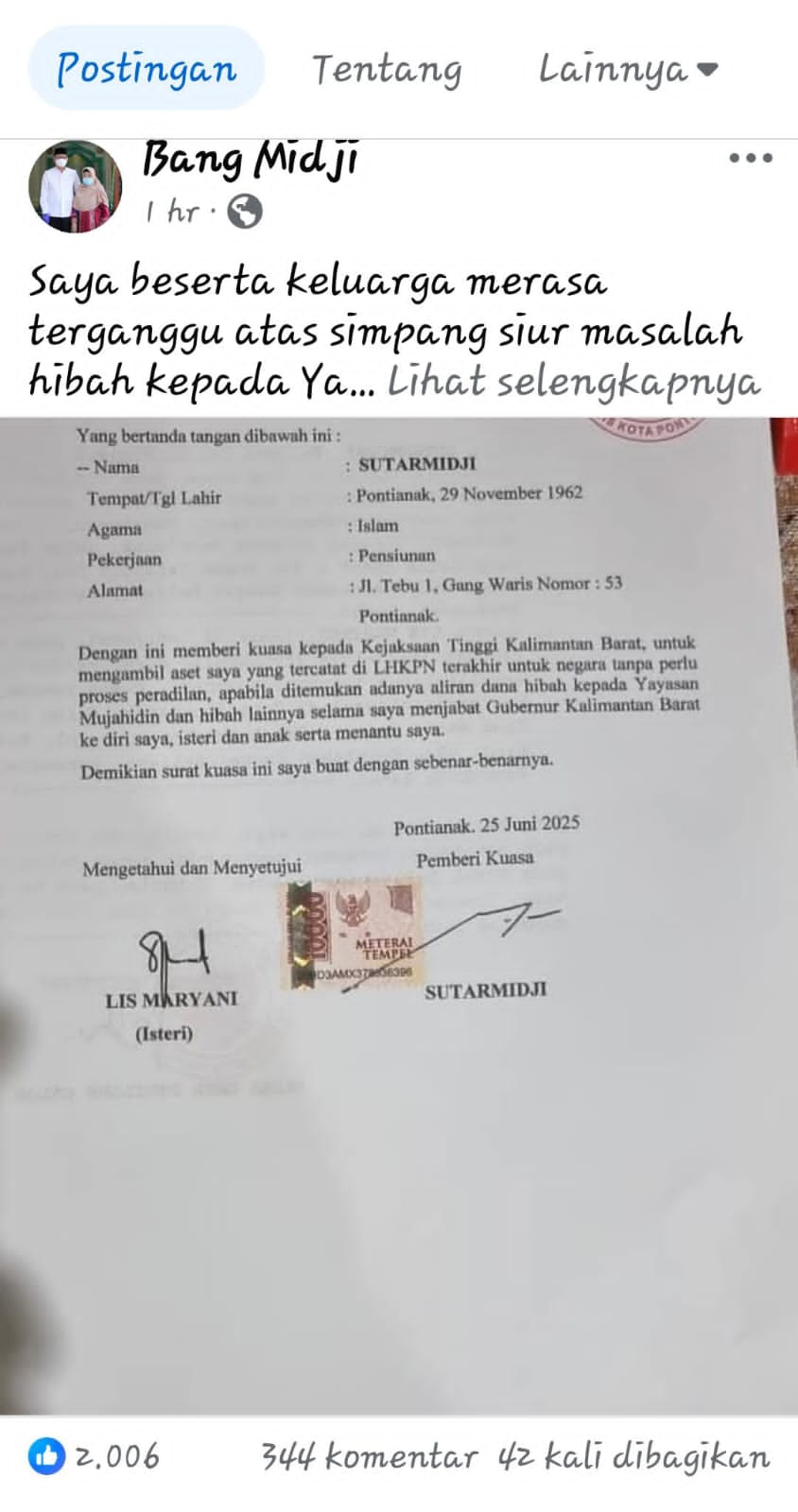Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Tanggal 2 Januari 2026 merupakan keberlakuan awal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiga undang-undang tersebut menjadi wajah baru dalam keberlakuan hukum pidana materil dan formil di Indonesia.
Bukan sekadar pergantian rezim undang-undang secara formal administratif, tujuan dari dibentuknya KUHP dan KUHAP baru yakni untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang bersifat modern yang memiliki ciri antara lain korektif, rehabilitatif, demokratisasi, dekolonialisasi, dan restoratif. Di lain sisi, tujuan dari diundangkan ketiga undang-undang ini juga ingin mengadopsi sejumlah ketentuan nilai yang hidup di masyarakat namun tetap berlandaskan pada pelindungan hak asasi manusia.
Beberapa ketentuan ketiga undang-undang tersebut pun tak lepas dari sorotan kritis dari masyarakat sipil. Di antara respons tersebut banyak menyoroti soal ketentuan dalam KUHP dan KUHAP yang berpotensi disalahgunakan dalam praktik di lapangan dan mengancam pelindungan terhadap kebebasan sipil sekaligus memperluas kewenangan dari penegak hukum.
Oleh karena itu, pemerintah mengadakan konferensi pers dalam merespons sejumlah kritikan tersebut (Kompas, 05/01). Terdapat 24 isu krusial yang dibahas yakni 7 poin dari KUHP dari mulai keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, delik penghinaan Presiden, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, sampai perzinahan dan minuman keras.
Dalam hal KUHAP, terdapat 12 isu krusial dari mulai hak tersangka dan terdakwa, praperadilan, upaya paksa, restorative justice dan penundaan penuntutan bagi korporasi, hingga hak kelompok rentan serta penggunaan persidangan yang berbasiskan pada teknologi. Sementara itu terdapat lima isu krusial yang berkenaan dengan Undang-Undang Penyesuaian Pidana seperti konversi penjatuhan pidana dan penyesuaian pidana narkotika.
Kendati beberapa aturan pelaksana dari KUHP dan KUHAP yang masih terus digodok, di lain sisi gugatan dari sejumlah pihak yang mempersoalkan tentang substansi dari ketentuan KUHP dan KUHAP melalui jalur judicial review pun terus bermunculan dan akan terus bermunculan dalam beberapa waktu ke depan.
Hal ini menjadi patut dinanti sebab melalui jalur judicial review inilah menjadi salah satu sarana yang ideal menyaksikan adu argumentasi dari pemerintah dan DPR dan warga masyarakat yang merasa dirugikan dengan keberlakuan suatu norma ataupun ketentuan dalam undang-undang.
MK Perlu Menjawab
Pada prinsipnya, sama seperti peradilan lainnya, MK tidak boleh menolak untuk mengadili perkara yang diajukan. Dalam hal ini, MK berkewajiban untuk mengadili seluruh perkara yang diajukan tentang apapun itu soal KUHP dan KUHAP. Prinsip ini merupakan prinsip ius curia novit yang merupakan prinsip dalam hukum acara.
Di sini, posisi antara pembentuk UU, yakni pemerintah dan DPR dan warga negara lain sejatinya sama. Berbeda dalam proses penyusunan undang-undang yang senyatanya tidak seimbang secara akses antara warga masyarakat dan pembentuk undang-undang.
MK pun berkewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutus semua gugatan soal KUHP dan KUHAP secara proporsional dan adil. Hal ini bukan berarti selalu melawan status quo, akan tetapi menurut penulis di sini MK perlu mengadili dan berikhtiar untuk menciptakan putusan yang akuntabel, rasional, serta disertai dengan logika penalaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di lain sisi, ini juga menjadi PR bagi pembentuk UU, yakni pemerintah dan DPR guna menghadirkan argumentasi yang kokoh, akuntabel, dan berbasiskan pada realitas guna merespons gugatan dari para pemohon.
Sebab, persidangan di MK, selain menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat luas, ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menilai kinerja dari pemegang amanah mereka dalam membentuk undang-undang. Selain itu, dalam perdebatan yang sehat dalam persidangan tak jarang memantik diskusi yang baik dalam pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum di masa depan.
Dalam sejarahnya, MK pernah mengadili beberapa perkara soal KUHP dan KUHAP lama. Sebagai contoh antara lain dalam Putusan 13-22/PUU-IV/2006 MK membatalkan Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP soal penghinaan terhadap Presiden dan wakil Presiden.
Begitu pula dalam Putusan 6/PUU-V/2007 MK juga membatalkan Pasal 154 dan 155 KUHP yang mengatur mengenai ujaran kebencian terhadap pemerintahan. Lebih lanjut, dalam Putusan 78/PUU-XXI/2023 MK menafsirkan Pasal 310 Ayat (1) KUHP tentang ujaran kebencian yang dilakukan secara lisan serta membatalkan Pasal 14 dan 15 UU 1 Tahun 1946 yang mengatur soal penyebaran berita bohong yang mengakibatkan keonaran di masyarakat.
Sementara itu mengenai ketentuan dalam hukum formil pidana sebagaimana yang diatur melalui KUHAP Tahun 1981, setidaknya MK telah sembilan kali menafsirkan ulang KUHAP. Dari sembilan kali penafsiran tersebut terdiri atas dua pembatalan norma secara keseluruhan yakni terhadap Pasal 83 ayat (2) tentang banding terhadap praperadilan akibat penghentian penyidikan dan penuntutan serta terhadap Pasal 268 ayat (3) tentang permohonan banding yang dapat diajukan sekali.
Sisanya terdiri atas tujuh putusan yang merupakan bentuk penafsiran terhadap suatu norma secara bersyarat diantaranya: objek praperadilan yang juga meliputi penetapan tersangka, ketentuan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup harus berdasarkan pada ketentuan kriteria alat bukti, dan diakuinya saksi yang tidak melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung atau Testimonium de auditu secara terbatas.
Menerka Posisi MK
Sejatinya, dalam pembentukan KUHP dan KUHAP baru, para pembentuk UU telah mengadopsi beberapa putusan MK sebelumnya. Hal ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi penggugat apabila ingin mengajukan beberapa ketentuan yang merupakan bentuk adopsi dari putusan MK sebelumnya.
Terlepas dari apapun dalil dan cara pembuktian para pihak dalam persidangan, menanti bagaimana proses MK ketika mengadili perkara ini. Salah satu isu penting ialah bagaimana cara MK untuk menafsirkan uji formil dalam pembentukan UU KUHAP. Sebab, pengujian formil memang memiliki tingkat kesulitan tersendiri untuk dibuktikan karena berkaitan dengan proses pembentukan Undang-Undang, bukan terhadap substansi secara langsung.
Terlebih, berkaca dari beberapa putusan uji formil sebelumnya tidak pernah ada pembatalan secara seketika terhadap keberlakuan uu melalui jalur uji formil. Memang, MK pernah dua kali menyatakan terjadi cacat prosedur dalam pembentukan Undang-Undang yakni dalam pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Kendati terbukti sebagai cacat prosedur, tetapi MK tidak mencabut keberlakuan kedua uu tersebut. Dalam UU MA 2009, memang terjadi cacat prosedur akan tetapi demi kepastian hukum keberlakuan UU tersebut tidak dinyatakan dicabut oleh MK.
Begitu pula terhadap UU Cipta Kerja 2020 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan untuk segera melakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun. Terakhir, uji formil UU TNI 2025 yang ditolak walaupun terdapat empat hakim menyatakan disenting opinion.
Maka tugas berat bagi pemohon untuk membuktikan cacat prosedur dan juga membatalkan keberlakuan dari KUHAP tersebut. Di lain sisi, butuh itu juga memerlukan keberanian hakim untuk menciptakan terobosan terhadap standar uji formil. Terlebih, tantangan yang akan dihadapi adalah penundaan KUHAP akan menyebabkan terganggunya kepastian hukum acara pidana.
Dalam uji materil, patut dinantikan bagaimana cara MK untuk melakukan penafsiran utamanya pasca keberlakuan KUHP dan KUHAP. Pada 2023, MK menyatakan semua permohonan yang berkenaan dengan KUHP sebagai prematur sehingga menjadi kehilangan objek.
Menurut penulis MK perlu mengadili semua perkara tersebut secara proporsional, rasional, dan akuntabel. Maksudnya, proses tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademis dan praktik. Oleh karenanya, penting kiranya MK untuk mendasari putusan tersebut dengan ratio desidendi dengan model penafsiran hukum dan standar uji proporsionalitas yang konsisten.
Sebab, itulah fungsi MK, bila nyatanya memang terbukti ada norma yang merupakan kesepakatan pembentuk uu justru menimbulkan tirani mayoritas ataupun bertentangan dengan UUD dan hak asasi, maka sudah seharusnya hal itu dibatalkan ataupun ditafsirkan ulang. Lagi-lagi, ini perlu dilakukan dengan ketat agar tidak menjadikan MK sebagai lembaga yang melanggengkan otoritarianisme itu sendiri.
Ke depan, keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, dan tanpa terkecuali para penegak hukum dan pembentuk uu amat sangat diperlukan untuk mengawasi proses peradilan di MK. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penyusunan permohonan yang kokoh jika akan mengajukan permohonan, pemberian keterangan dan jawaban yang rasional dari penegak hukum dan pembentuk uu, serta pemantauan secara berkala terhadap jalannya persidangan.
(miq/miq)

 3 hours ago
1
3 hours ago
1