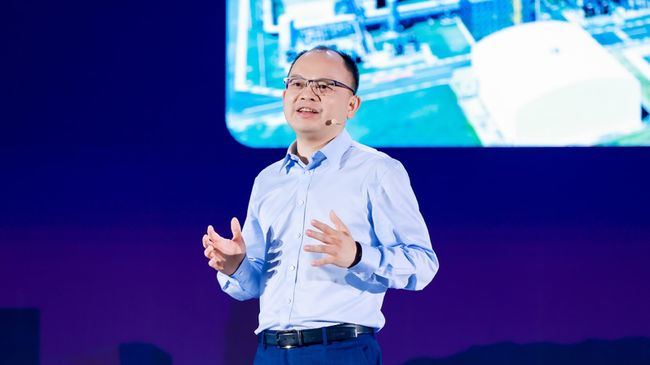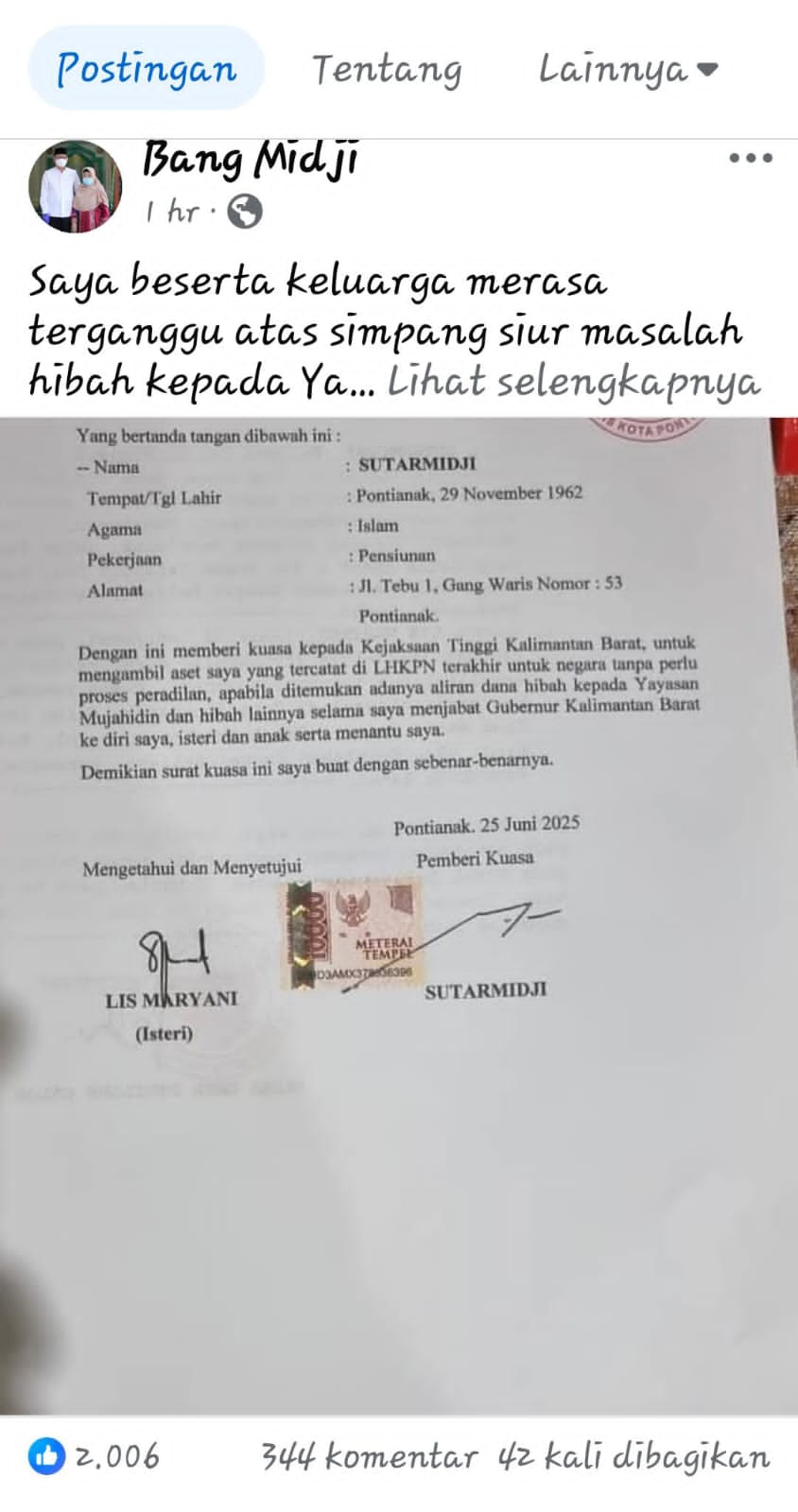Jakarta, CNBC Indonesia - Jaksa Korea Selatan untuk pertama kalinya dalam 30 tahun menuntut hukuman mati terhadap seorang mantan kepala negara. Tuntutan itu diajukan terhadap mantan Presiden Yoon Suk Yeol atas perannya dalam deklarasi darurat militer yang gagal pada Desember 2024, sebuah langkah yang oleh penuntut disebut sebagai ancaman langsung terhadap tatanan konstitusional negara.
Dalam persidangan di Pengadilan Distrik Pusat Seoul, jaksa menggambarkan perkara ini sebagai "penghancuran serius terhadap tatanan konstitusional oleh kekuatan anti-negara". Mereka menyatakan Yoon telah "secara langsung dan fundamental melanggar keselamatan negara serta kelangsungan hidup dan kebebasan rakyat".
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Korea Selatan, tuduhan sebagai pemimpin pemberontakan hanya membuka tiga kemungkinan hukuman: hukuman mati, penjara seumur hidup dengan kerja paksa, atau penjara seumur hidup tanpa kerja paksa. Majelis hakim dijadwalkan membacakan putusan pada 19 Februari mendatang.
Selain Yoon, jaksa juga menuntut hukuman penjara seumur hidup dengan kerja paksa bagi mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun. Ia disebut telah "bergerak sebagai satu tubuh" dengan Yoon sepanjang konspirasi tersebut.
Kasus ini berpusat pada keputusan Yoon mengerahkan pasukan militer ke Majelis Nasional pada malam 3 Desember 2024. Jaksa menuduh Yoon memerintahkan tentara untuk mencegah para anggota parlemen melakukan pemungutan suara guna mencabut deklarasi darurat militernya.
Krisis yang berlangsung sekitar enam jam itu berakhir ketika 190 anggota parlemen berhasil menembus barikade militer dan mengesahkan resolusi darurat, yang secara efektif memaksa Yoon menarik kembali keputusannya. Parlemen kemudian memakzulkan Yoon pada 14 Desember, dan Mahkamah Konstitusi secara resmi mencopotnya dari jabatan pada April 2025.
Pemilu kilat yang digelar setelah pemecatan tersebut mengantarkan rival politik Yoon, Lee Jae Myung, ke kursi presiden.
Dalam paparan di persidangan, jaksa menyebut Yoon mulai merancang operasi darurat militer itu bahkan sebelum Oktober 2023, dengan tujuan "memonopoli kekuasaan melalui pemerintahan jangka panjang". Mereka mengatakan Yoon secara strategis menempatkan personel militer di posisi-posisi kunci sebelum deklarasi diberlakukan.
Menurut argumen penutup jaksa, rencana-rencana itu terdokumentasi dalam buku catatan dan memo ponsel, termasuk skenario menyiapkan penyiksaan terhadap pejabat pemilu agar mengakui kecurangan pemilu yang direkayasa, serta rencana memutus pasokan listrik dan air ke media-media penting.
"Jika hanya satu [anggota kabinet] saja memberi tahu dunia luar ... penerapan darurat militer akan menjadi mustahil secara realistis," kata jaksa di hadapan pengadilan, Rabu (14/1/2026), dilansir The Guardian.
Mereka mengecam para pejabat senior yang "memilih kesetiaan kepada Yoon dan keserakahan untuk berbagi kekuasaan", serta dinilai telah mengancam nyawa dan kebebasan masyarakat.
Jaksa juga menyoroti tidak adanya penyesalan dari Yoon sebagai faktor yang memberatkan. Menurut mereka, Yoon tidak pernah benar-benar meminta maaf dan justru menyalahkan oposisi saat itu, sembari menghasut para pendukungnya.
Sebagian dari para pendukung tersebut kemudian menyerbu gedung pengadilan dalam aksi protes kekerasan setelah Yoon ditangkap.
Sebagai mantan jaksa agung, Yoon disebut sepenuhnya menyadari bahwa deklarasi darurat militer tersebut bertentangan dengan konstitusi.
Menanggapi proses hukum yang berjalan, kantor kepresidenan dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa lembaga peradilan akan menjatuhkan putusan sesuai dengan hukum dan prinsip yang berlaku, serta sejalan dengan harapan publik.
Perkara ini menjadi kasus pertama terkait tuduhan pemberontakan terhadap mantan presiden sejak persidangan tahun 1996 terhadap dua mantan diktator militer, Chun Doo-hwan dan Roh Tae-woo, atas peran mereka dalam kudeta 1979 dan pembantaian di Gwangju.
Pada saat itu, jaksa menuntut hukuman mati bagi Chun dan penjara seumur hidup bagi Roh. Keduanya dinyatakan bersalah, meski kemudian hukumannya diringankan dan akhirnya mendapat pengampunan.
Korea Selatan sendiri tidak pernah mengeksekusi terpidana mati sejak 1997 dan oleh kelompok hak asasi manusia diklasifikasikan sebagai negara "penghapus hukuman mati secara de facto".
Yoon pertama kali ditangkap pada Januari 2025, menjadikannya presiden Korea Selatan pertama yang ditahan saat masih menjabat. Ia sempat dibebaskan pada Maret setelah pengadilan membatalkan penahanannya, namun kembali ditangkap pada Juli dan sejak itu ditahan.
Perkara pemberontakan ini hanyalah satu bagian dari gelombang proses hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiga penyelidikan jaksa khusus yang berjalan bersamaan, menyangkut Yoon, istrinya, serta dugaan penutupan kasus kematian seorang marinir, telah menyeret lebih dari 120 orang dari kalangan politik dan militer sebagai terdakwa.
Secara keseluruhan, Yoon menghadapi delapan persidangan pidana terpisah, dengan dakwaan mulai dari penyalahgunaan kekuasaan hingga pelanggaran undang-undang pemilu. Di luar tuduhan pemberontakan, ia juga dituduh memerintahkan infiltrasi drone ke wilayah udara Pyongyang pada akhir 2024, yang diduga dimaksudkan untuk memprovokasi Korea Utara dan menciptakan dalih pemberlakuan darurat militer.
Sementara itu, istrinya, Kim Keon Hee, akan menghadapi putusan pengadilan pada 28 Januari terkait tuduhan manipulasi saham dan suap. Jaksa dalam perkara tersebut menuntut hukuman 15 tahun penjara.
Putusan pertama terhadap Yoon dijadwalkan dibacakan pada 16 Januari dalam kasus penghalangan penangkapan, di mana jaksa menuntut hukuman 10 tahun penjara.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

 2 hours ago
1
2 hours ago
1